Menambah kata “Sayyid” sebelum menyebut nama Nabi Muhammad adalah perkara yang dibolehkan di dalam syari’at. Karena pada kenyataannya Rasulullah adalah seorang Sayyid, bahkan beliau adalah Sayyid al-‘Alamin, penghulu dan pimpinan seluruh makhluk. Salah seorang ulama bahasa terkemuka, ar-Raghib al-Ashbahani dalam kitab Mufradat Alfazh al-Qur’an, menuliskan bahwa di antara makna “Sayyid” adalah seorang pemimpin, seorang yang membawahi perkumpulan satu kaum yang dihormati dan dimuliakan (Mu’jam Mufradat Alfazh al-Qur’an, hal. 254).
Dalam al-Qur’an, Allah menyebut Nabi Yahya dengan kata “Sayyid”:
وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (ءال عمران: 39)
“… menjadi pemimpin dan ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh”. (QS. Ali ‘Imran: 39)
Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari pada Nabi Yahya, karena beliau adalah pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Dengan demikian mengatakan “Sayyid” bagi Nabi Muhammad tidak hanya boleh, tapi sudah selayaknya, karena beliau lebih berhak untuk itu. Bahkan dalam sebuah hadits, Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang “Sayyid”. Beliau bersabda:
أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ ءَادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ (رواه الترمذي)
“Saya adalah penghulu manusia di hari kiamat”. (HR. at-Tirmidzi)
Dengan demikian di dalam membaca shalawat boleh bagi kita mengucapkan “Allahumma Shalli ‘Ala Sayyidina Muhammad”, meskipun tidak ada pada lafazh-lafazh shalawat yang diajarkan oleh Nabi (ash-Shalawat al Ma’tsurah) dengan penambahan kata “Sayyid”. Karena menyusun dzikir tertentu yang tidak ma’tsur boleh selama tidak bertentangan dengan yang ma’tsur.
Sahabat ‘Umar ibn al-Khaththab dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menambah lafazh talbiyah dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Lafazh talbiyah yang diajarkan oleh Nabi adalah:
لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ
Namun kemudian sabahat Umar ibn al-Khaththab menambahkannya. Dalam bacaan beliau:
لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
Dalil lainnya adalah dari sahabat ‘Abdullah ibn ‘Umar bahwa beliau membuat kalimat tambahan pada Tasyahhud di dalamnya shalatnya. Kalimat Tasyahhud dalam shalat yang diajarkan Rasulullah adalah “Asyhadu An La Ilaha Illah, Wa Asyhadu Anna Muhammad Rasulullah”. Namun kemudian ‘Abdullah ibn ‘Umar menambahkan Tasyahhud pertamanya menjadi:
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ
Tambahan kalimat “Wahdahu La Syarika Lah” sengaja diucapkan oleh beliau. Bahkan tentang ini ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata: “Wa Ana Zidtuha…”. Artinya: “Saya sendiri yang menambahkan kalimat “Wahdahu La Syarika Lah”. (HR Abu Dawud)
Dalam sebuah hadits shahih, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Rifa’ah ibn Rafi’, bahwa ia (Rifa’ah ibn Rafi’) berkata: “Suatu hari kami shalat berjama’ah di belakang Rasulullah. Ketika beliau mengangkat kepala setelah ruku’ beliau membaca: “Sami’allahu Liman Hamidah”, tiba-tiba salah seorang makmum berkata:
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ
Setelah selesai shalat Rasulullah bertanya: “Siapakah tadi yang mengatakan kalimat-kalimat itu?”. Orang yang yang dimaksud menjawab: “Saya Wahai Rasulullah…”. Lalu Rasulullah berkata:
رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ
“Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya”.
al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitab Fath al-Bari, dalam menjelaskan hadits sahabat Rifa’ah ibn Rafi ini menuliskan sebagai berikut: “Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan kepada beberapa perkara.
Pertama: Menunjukan kebolehan menyusun dzikir yang tidak ma’tsur di dalam shalat selama tidak menyalahi yang ma’tsur.
Dua: Boleh mengeraskan suara dzikir selama tidak mengganggu orang lain di dekatnya. Tiga; Bahwa orang yang bersin di dalam shalat diperbolehkan baginya mengucapkan “al-Hamdulillah” tanpa adanya hukum makruh” (Fath al-Bari, juz 2 hal. 287).
Dengan demikian boleh hukumnya dan tidak ada masalah sama sekali di dalam bacaan shalawat menambahkan kata “Sayyidina”, baik dibaca di luar shalat maupun di dalam shalat. Karena tambahan kata “Sayyidina” ini adalah tambahan yang sesuai dengan dasar syari’at, dan sama sekali tidak bertentangan dengannya.
Asy-Syaikh al’Allamah Ibn Hajar al-Haitami dalam kitab al-Minhaj al-Qawim, halaman 160, menuliskan sebagai berikut:
وَلاَ بَأْسَ بِزِيَادَةِ سَيِّدِنَا قَبْلَ مُحَمَّدٍ، وَخَبَرُ”لاَ تُسَيِّدُوْنِي فِيْ الصَّلاَةِ” ضَعِيْفٌ بَلْ لاَ أَصْلَ لَهُ
“Dan tidak mengapa menambahkan kata “Sayyidina” sebelum Muhammad. Sedangkan hadits yang berbunyi “La Tusyyiduni Fi ash-Shalat” adalah hadits dla’if bahkan tidak memiliki dasar (hadits maudlu/palsu)”.
Di antara hal yang menunjukan bahwa hadits “La Tusayyiduni Fi ash-Shalat” sebagai hadits palsu (Maudlu’) adalah karena di dalam hadits ini terdapat kaedah kebahasaan yang salah (al-Lahn). Artinya, terdapat kalimat yang ditinjau dari gramatika bahasa Arab adalah sesuatu yang aneh dan asing. Yaitu pada kata “Tusayyiduni”. Di dalam bahasa Arab, dasar kata “Sayyid” adalah berasal dari kata “Saada, Yasuudu”, bukan “Saada, Yasiidu”.
Dengan demikian bentuk fi’il Muta’addi (kata kerja yang membutuhkan kepada objek) dari “Saada, Yasuudu” ini adalah “Sawwada, Yusawwidu”, dan bukan “Sayyada, Yusayyidu”. Dengan demikian, -seandainya hadits di atas benar adanya-, maka bukan dengan kata “La Tasayyiduni”, tapi harus dengan kata “La Tusawwiduni”. Inilah yang dimaksud dengan al-Lahn. Sudah barang tentu Rasulullah tidak akan pernah mengucapkan al-Lahn semacam ini, karena beliau adalah seorang Arab yang sangat fasih (Afshah al-‘Arab).
Bahkan dalam pendapat sebagian ulama, mengucapkan kata “Sayyidina” di depan nama Rasulullah, baik di dalam shalat maupun di luar shalat lebih utama dari pada tidak memakainya. Karena tambahan kata tersebut termasuk penghormatan dan adab terhadap Rasulullah. Dan pendapat ini dinilai sebagai pendapat mu’tamad.
Asy-Syaikh al-‘Allamah al-Bajuri dalam kitab Hasyiah al-Bajuri, menuliskan sebagai berikut:
الأوْلَى ذِكْرُ السِّيَادَةِ لأَنّ الأفْضَلَ سُلُوْكُ الأدَبِ، خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ الأوْلَى تَرْكُ السّيَادَةِ إقْتِصَارًا عَلَى الوَارِدِ، وَالمُعْتَمَدُ الأوَّلُ، وَحَدِيْثُ لاَ تُسَوِّدُوْنِي فِي صَلاتِكُمْ بِالوَاوِ لاَ بِاليَاءِ بَاطِلٌ
“Yang lebih utama adalah mengucapkan kata “Sayyid”, karena yang lebih afdlal adalah menjalankan adab. Hal ini berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa lebih utama meninggalkan kata “Sayyid” dengan alasan mencukupkan di atas yang warid saja. Dan pendapat mu’tamad adalah pendapat yang pertama. Adapun hadits “La Tusawwiduni Fi Shalatikum”, yang seharusnya dengan “waw” (Tusawwiduni) bukan dengan “ya” (Tusayyiduni) adalah hadits yang batil” (Hasyiah al-Bajuri, juz 1 hal. 156)
Islam ahlussunnah wal jama'ah adalah Islam dg 4 ciri: 1. berpedoman pada Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. 2. Di bidang Fiqih, bermadzhab kepada salah satu madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali). 3. Di bidang Aqidah, mengikuti faham Asy'ariyah dan Maturidiyah. 4. Di bidang Tasawuf, mengikuti Imam Abu Qosim al-Junaidi
Allah

Mari selalu dzikir kepada Allah setiap waktu
Senin, 30 Agustus 2010
DALIL QUR'AN ANJURAN MENGGUNAKAN SAYYID SEBELUM KATA MUHAMMAD SAW.
Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 63
“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebahagian (yang lain)”. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur- angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
Kata “kamu” yang dimaksud dalam ayat diatas adalah sahabat Rasul, orang muslim atau umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang munafik atau orang kafir/musyrik Quraisy.
Karena saat itu orang kafir/musyrik Quraisy memanggil Rosul dengan sebutan yang merendahkan Nabi Muhammad SAW.
Dalam ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa janganlah kamu memanggil Rasul atau Nabi sama seperti kita memanggil teman kita sendiri.
Misalkan kita punya teman namanya “Budi”, lalu kita menyapa : Budi apa kabar?, atau Pak Budi, Mas Budi atau Dik Budi apa khabar? Itu kepada teman kita.
Lalu bagaimana cara memanggil atau menyebut Nabi/Rasul? Caranya ya jangan seperti kita menyebut/memanggil teman kita seperti diatas:
1. Bisa menggunakan kata-kata “sayyidinaa” didepan namanya, misalkan sayyidinaa Muhammad SAW. Contohnya :Allahumma salli ‘ala sayyidinaa Muhammad wa ‘ala ali sayyidinaa Muhammad.
“Aku junjungan (sayyid) bagi semua anak-cucu Adam as, dan aku mengatakannya tanpa kesombongan” …diriwayatkan oleh al-Syaykhâni (al-Bukhârî dan Muslim)
2. Atau menggunakan kata-kata “Rosulullah” didepan namanya, atau dibelakang namanya, misalkan ‘Rosulullah Muhammad saw’ atau ‘Muhammad Rosulullah’
Contohnya :Allahumma salli ‘ala Rosulillah Muhammad saw. wa ‘ala alihi wa shohbihi wa dhurriyyaatihi.
Contoh lain : Dalam dua kalimat syahadat (yang sering digunakan untuk adzan dan iqamah) “Asyhadu anlaa ilaaha illaloh, wa asyhadu anna Muhammad-’Rasulullah’.
Lantas bagaimana mengucapkan sholawat nabi di dalam sholat?, sebagaimana hadist nabi : Sholatlah kalian sebagaimana (kalian) melihat aku sholat (HR Bukhori, Muslim, Ahmad).
Bukankah Nabi sendiri didalam sholat ketika membaca sholawat menyebut nama beliau sendiri tanpa menggunakan sayyidina?
Untuk kasus ini kita harus tahu diri, harus ngaca diri artinya tahu siapa diri kita dan tahu siapa nabi. Disini kita harus menggunakan akal pikiran logika kita, kita harus tahu adab dan sopan santun terhadap nabi.
….dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. (QS. Yunus :100)
Seseorang saja kalau dia keturunan ningrat, bangsawan atau masih ada keturunan darah biru terkadang orang itu mencantumkan gelar kebangsawanannya misalkan “raden”, “roro”, “tubagus” dll di depan namanya.
INGAT: PENGHORMATAN BUKAN BERARTI PENYEMBAHAN ATAU PENGKULTUSAN
“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebahagian (yang lain)”. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur- angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
Kata “kamu” yang dimaksud dalam ayat diatas adalah sahabat Rasul, orang muslim atau umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang munafik atau orang kafir/musyrik Quraisy.
Karena saat itu orang kafir/musyrik Quraisy memanggil Rosul dengan sebutan yang merendahkan Nabi Muhammad SAW.
Dalam ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa janganlah kamu memanggil Rasul atau Nabi sama seperti kita memanggil teman kita sendiri.
Misalkan kita punya teman namanya “Budi”, lalu kita menyapa : Budi apa kabar?, atau Pak Budi, Mas Budi atau Dik Budi apa khabar? Itu kepada teman kita.
Lalu bagaimana cara memanggil atau menyebut Nabi/Rasul? Caranya ya jangan seperti kita menyebut/memanggil teman kita seperti diatas:
1. Bisa menggunakan kata-kata “sayyidinaa” didepan namanya, misalkan sayyidinaa Muhammad SAW. Contohnya :Allahumma salli ‘ala sayyidinaa Muhammad wa ‘ala ali sayyidinaa Muhammad.
“Aku junjungan (sayyid) bagi semua anak-cucu Adam as, dan aku mengatakannya tanpa kesombongan” …diriwayatkan oleh al-Syaykhâni (al-Bukhârî dan Muslim)
2. Atau menggunakan kata-kata “Rosulullah” didepan namanya, atau dibelakang namanya, misalkan ‘Rosulullah Muhammad saw’ atau ‘Muhammad Rosulullah’
Contohnya :Allahumma salli ‘ala Rosulillah Muhammad saw. wa ‘ala alihi wa shohbihi wa dhurriyyaatihi.
Contoh lain : Dalam dua kalimat syahadat (yang sering digunakan untuk adzan dan iqamah) “Asyhadu anlaa ilaaha illaloh, wa asyhadu anna Muhammad-’Rasulullah’.
Lantas bagaimana mengucapkan sholawat nabi di dalam sholat?, sebagaimana hadist nabi : Sholatlah kalian sebagaimana (kalian) melihat aku sholat (HR Bukhori, Muslim, Ahmad).
Bukankah Nabi sendiri didalam sholat ketika membaca sholawat menyebut nama beliau sendiri tanpa menggunakan sayyidina?
Untuk kasus ini kita harus tahu diri, harus ngaca diri artinya tahu siapa diri kita dan tahu siapa nabi. Disini kita harus menggunakan akal pikiran logika kita, kita harus tahu adab dan sopan santun terhadap nabi.
….dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. (QS. Yunus :100)
Seseorang saja kalau dia keturunan ningrat, bangsawan atau masih ada keturunan darah biru terkadang orang itu mencantumkan gelar kebangsawanannya misalkan “raden”, “roro”, “tubagus” dll di depan namanya.
INGAT: PENGHORMATAN BUKAN BERARTI PENYEMBAHAN ATAU PENGKULTUSAN
HUKUM SHOLAT BERJAMA'AH
Di kalangan ulama memang berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjamaah. Ada yang mengatakan fardhu `ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardhu kifayah sehingga bila sudah ada shalat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus shalat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.
Tentu masing-masing pendapat itu ada benarnya, sebab mereka telah berijtihad dengan memenuhi kaidah istimbath hukum yang benar. Kalau pun hasilnya berbeda-beda, tentu karena hal ini adalah ijtihad. Sebab tidak ada lafadz yang secara eksplisit di dalam Al-Quran atau hadits yang menyebutkan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya begini dan begini.
Yang ada hanya sekian banyak dalil yang masih mungkin menerima ragam kesimpulan yang berbeda. Dan sebenarnya hal seperti ini sangat lumrah di dunia fiqih, kita pun tidak perlu terlalu risau bila ada pendapat dari ulama yang ternyata tidak sejalan dengan apa yang kita pahami selama ini. Atau berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru kita selama ini.
Dan berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam ilmu syariah.
1. Pendapat Pertama: Fardhu Kifayah
Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi`i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah juz 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur ulama baik yang lampau maupun yang berikutnya . Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.
Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.
Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa:
Shalat jamaah itu itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.
Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah:
Dari Abi Darda` ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya.
Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam. .
Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.
Al-Khatthabi dalam kitab Ma`alimus-Sunan juz 1 halaman 160 berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi`i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu `ain dengan berdasarkan hadits ini.
2. Pendapat Kedua: Fardhu `Ain
Yang berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auza`i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatanginya untuk shalat. .
Dalilnya adalah hadits berikut:
Dari Aisyah ra berkata, Siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya , maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya.
Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia berdoa namun shalatnya tetap syah.
Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. .
3. Pendapat Ketiga: Sunnah Muakkadah
Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar juz 3 halaman 146. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu `ain, fardhu kifayah atau syarat syahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.
Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. .
Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Lihat Jawahirul Iklil jilid 1 halama 76.
Ibnul Jauzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah. . Ad-Dardir dalam kitab Asy-Syarhu As-Shaghir juz 1 halaman 244 berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah.
Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini:
Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.
Ash-Shan`ani dalam kitabnya Subulus-Salam juz 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.
Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini:
Dari Abi Musa ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur.
4. Pendapat Keempat: Syarat Syahnya Shalat
Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat syahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak sah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.
Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya . Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyah . Termasuk di antaranya adalah sebagian dari ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah.
Dalil yang mereka gunakan adalah:
Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw bersaba, Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.
Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. .
Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah saw berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah saw memanggilnya dan bertanya, Apakah kamu dengar azan shalat? Ya, jawabnya. Datangilah, kata Rasulullah saw.
dan ikutilah fatwa yg anda yakini, semua hasil ijtihad di atas berdasarkan hadits2 Nabi saw., dan perbedaan hukum ini hanyalah masalah furu'iyah tidak perlu dipertentangkan, setiap orang berhak mengikuti madzhab mana yg diyakininya
Tentu masing-masing pendapat itu ada benarnya, sebab mereka telah berijtihad dengan memenuhi kaidah istimbath hukum yang benar. Kalau pun hasilnya berbeda-beda, tentu karena hal ini adalah ijtihad. Sebab tidak ada lafadz yang secara eksplisit di dalam Al-Quran atau hadits yang menyebutkan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya begini dan begini.
Yang ada hanya sekian banyak dalil yang masih mungkin menerima ragam kesimpulan yang berbeda. Dan sebenarnya hal seperti ini sangat lumrah di dunia fiqih, kita pun tidak perlu terlalu risau bila ada pendapat dari ulama yang ternyata tidak sejalan dengan apa yang kita pahami selama ini. Atau berbeda dengan apa yang diajarkan oleh guru kita selama ini.
Dan berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam ilmu syariah.
1. Pendapat Pertama: Fardhu Kifayah
Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi`i dan Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah juz 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur ulama baik yang lampau maupun yang berikutnya . Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.
Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.
Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa:
Shalat jamaah itu itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.
Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah:
Dari Abi Darda` ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya.
Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam. .
Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.
Al-Khatthabi dalam kitab Ma`alimus-Sunan juz 1 halaman 160 berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi`i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu `ain dengan berdasarkan hadits ini.
2. Pendapat Kedua: Fardhu `Ain
Yang berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auza`i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar azan, haruslah dia mendatanginya untuk shalat. .
Dalilnya adalah hadits berikut:
Dari Aisyah ra berkata, Siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya , maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya.
Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia berdoa namun shalatnya tetap syah.
Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. .
3. Pendapat Ketiga: Sunnah Muakkadah
Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar juz 3 halaman 146. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu `ain, fardhu kifayah atau syarat syahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.
Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. .
Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Lihat Jawahirul Iklil jilid 1 halama 76.
Ibnul Jauzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah. . Ad-Dardir dalam kitab Asy-Syarhu As-Shaghir juz 1 halaman 244 berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah.
Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini:
Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.
Ash-Shan`ani dalam kitabnya Subulus-Salam juz 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.
Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini:
Dari Abi Musa ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur.
4. Pendapat Keempat: Syarat Syahnya Shalat
Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat syahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak sah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.
Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya . Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyah . Termasuk di antaranya adalah sebagian dari ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah.
Dalil yang mereka gunakan adalah:
Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw bersaba, Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.
Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. .
Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah saw berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah saw memanggilnya dan bertanya, Apakah kamu dengar azan shalat? Ya, jawabnya. Datangilah, kata Rasulullah saw.
dan ikutilah fatwa yg anda yakini, semua hasil ijtihad di atas berdasarkan hadits2 Nabi saw., dan perbedaan hukum ini hanyalah masalah furu'iyah tidak perlu dipertentangkan, setiap orang berhak mengikuti madzhab mana yg diyakininya
Jumat, 27 Agustus 2010
UNTUK HAMBA ALLAH
Hadist ini diijazahkan (diberikan) kepadaku oleh Al-Allamah As-syekh
Muhammad Al-Khatib As-Syami Al-Madani Al-Hanbali, Yaitu Ibnu Utsman
bin Abbas bin Utsman, diterima dari para syekh beliau dengan sanad
muttasil (bersambung) sampai kepada Abu Dzar Al-Ghiffari r.a., dari
RASULULLAH SAW., beliau bersabda dalam hadits Qudsi bahwa Allah Azza
wa Jalla berfirman;
"Wahai hamba - hamba-Ku, ketahuilah bahwa Aku mengharamkan kezaliman
atas diri-Ku dan aku haramkan pula kezaliman itu pada kalian, maka
janganlah kalian saling aniaya.
Wahai, hamba - hamba-Ku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat,
kecuali orang yang Aku beri petunjuk. MAka mintalah petunjuk kepada-
Ku, niscaya Aku akan memberi kalian petunjuk.
Wahai hamba-hamba- Ku, kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang
Aku beri makan, maka mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku akan
memberi kalian makan.
Wahai hamba-hamba- Ku, kalian semua telanjang (tidak berpakaian),
kecuali orang yang Aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada-
Ku, niscaya Aku akan memberi kalian pakaian.
Wahai hamba-hamba- Ku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan, dimalam
dan siang hari, sementara Aku mengampuni segala dosa, maka mintalah
ampunan kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuni kalian.
Wahai hamba-hamba- Ku, sesungguhnya kalian tidak akanmampu
mendatangkan bahaya kepada-Ku, lalu melakukan yang kalian anggap
membahayakan Aku itu, dan kalian tidak pula mampu memberikan
kemanfaatan kepada-Ku, lalu kalian memberikan kemanfaatan itu kepada-
Ku.
Wahai hamba-hamba- Ku, seandainya kalian semua, mulai dari awal
hingga akhir baik bangsa jin maupun manusia, semuanayamenjadi orang -
orang yang bertaqwa, laksana ketaqwaan orang berhati paling taqwa
diantara kalian, maka semua itu tidak akan menambah sedikitpun pula
kerajaan-Ku.
Wahai hamba-hamba- Ku, seadainya kalian semua, mulai dari awal
hingga akhir baik bangsa jin maupun manusia, semuanayamenjadi orang -
orang yang durhaka, sebagaimana kedurhakaan orang yang paling
durhaka diantara kalian, maka semua itu tidak akan mengurangi
sedikitpun pula kerajaan-Ku.
Wahai hamba-hamba- Ku, andaikan kalian semua yang awal sampai yang
akhir, baik manusia dan jin, semuanya serempak berdiri di suatu
tempat untuk memohon kepada-Ku, lalu aku berikan pada tiap-tiap
orang akan permintaannya, niscaya semua itu tidak akan mengurangi
sedikitpun terhadap apa yang ada pada-Ku, selain laksana sebuah
jarum jahit bila dimasukkan ke lautan.
Wahai hamba-hamba- Ku, sesungguhnya semua itu adalah perbuatan kalian
yang Aku perhitungkan untuk kalian, kemudian Aku akan memberikan
secara penuh kepada kalian. Maka, barangsiapa mendapatkan kebaikan,
maka hendaklah memuji syukur kepada Allah dan barangsiapa yang
mendapatkan yang selain itu, maka janganlah mencela, selain pada
dirinya sendiri."
Muhammad Al-Khatib As-Syami Al-Madani Al-Hanbali, Yaitu Ibnu Utsman
bin Abbas bin Utsman, diterima dari para syekh beliau dengan sanad
muttasil (bersambung) sampai kepada Abu Dzar Al-Ghiffari r.a., dari
RASULULLAH SAW., beliau bersabda dalam hadits Qudsi bahwa Allah Azza
wa Jalla berfirman;
"Wahai hamba - hamba-Ku, ketahuilah bahwa Aku mengharamkan kezaliman
atas diri-Ku dan aku haramkan pula kezaliman itu pada kalian, maka
janganlah kalian saling aniaya.
Wahai, hamba - hamba-Ku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat,
kecuali orang yang Aku beri petunjuk. MAka mintalah petunjuk kepada-
Ku, niscaya Aku akan memberi kalian petunjuk.
Wahai hamba-hamba- Ku, kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang
Aku beri makan, maka mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku akan
memberi kalian makan.
Wahai hamba-hamba- Ku, kalian semua telanjang (tidak berpakaian),
kecuali orang yang Aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada-
Ku, niscaya Aku akan memberi kalian pakaian.
Wahai hamba-hamba- Ku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan, dimalam
dan siang hari, sementara Aku mengampuni segala dosa, maka mintalah
ampunan kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuni kalian.
Wahai hamba-hamba- Ku, sesungguhnya kalian tidak akanmampu
mendatangkan bahaya kepada-Ku, lalu melakukan yang kalian anggap
membahayakan Aku itu, dan kalian tidak pula mampu memberikan
kemanfaatan kepada-Ku, lalu kalian memberikan kemanfaatan itu kepada-
Ku.
Wahai hamba-hamba- Ku, seandainya kalian semua, mulai dari awal
hingga akhir baik bangsa jin maupun manusia, semuanayamenjadi orang -
orang yang bertaqwa, laksana ketaqwaan orang berhati paling taqwa
diantara kalian, maka semua itu tidak akan menambah sedikitpun pula
kerajaan-Ku.
Wahai hamba-hamba- Ku, seadainya kalian semua, mulai dari awal
hingga akhir baik bangsa jin maupun manusia, semuanayamenjadi orang -
orang yang durhaka, sebagaimana kedurhakaan orang yang paling
durhaka diantara kalian, maka semua itu tidak akan mengurangi
sedikitpun pula kerajaan-Ku.
Wahai hamba-hamba- Ku, andaikan kalian semua yang awal sampai yang
akhir, baik manusia dan jin, semuanya serempak berdiri di suatu
tempat untuk memohon kepada-Ku, lalu aku berikan pada tiap-tiap
orang akan permintaannya, niscaya semua itu tidak akan mengurangi
sedikitpun terhadap apa yang ada pada-Ku, selain laksana sebuah
jarum jahit bila dimasukkan ke lautan.
Wahai hamba-hamba- Ku, sesungguhnya semua itu adalah perbuatan kalian
yang Aku perhitungkan untuk kalian, kemudian Aku akan memberikan
secara penuh kepada kalian. Maka, barangsiapa mendapatkan kebaikan,
maka hendaklah memuji syukur kepada Allah dan barangsiapa yang
mendapatkan yang selain itu, maka janganlah mencela, selain pada
dirinya sendiri."
WAHAI ANAKKU... BERTAQWALAH KEPADA ALLAH ^_^
Anak merupakan amanah yang dititipkan kepada orang tua, mendidik anak dengan kebaikan juga merupakan investasi akhirat bagi orang tuanya. Artikel ini merupakan nasehat yang diambil dari kumpulan nasehat-nasehat dari Syaikh Ahmad as-Syakir dalam Washaya al-Aba' Lil Abna.
Wahai anakku...
Sesungguhnya Rabbmu mengetahui apa yang kamu betikkan dalam hatimu, dan Dia mengetahui apa yang engkau ucapkan dengan lisanmu, dan Dia melihat terhadap segala amalanmu, maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai anakku, dan berhati-hatilah kamu terhadap pengawasan-Nya pada saat kamu dalam keadaan yang tidak diridhai oleh-Nya.
Hati-hatilah kamu dari kemurkaan Rabbmu, yang mana Dialah yang telah menciptakanmu dan memberikan rizki kepadamu serta yang telah mengaruniai kamu akal yang dapat kamu gunakan di dalam kehidupanmu. Bagaimana perasaanmu ketika bapakmu melihat dirimu dalam keadaan melanggar perintahnya? Apakah kamu tidak khawatir nantinya bapakmu akan menghukummu? Maka jadikanlah perasaanmu sama seperti itu [bahkan lebih] kepada Allah, karena Dia dapat melihat dirimu disetiap kesempatan yang kamu tidak dapat melihat Dia! Maka janganlah kamu anggap enteng pada perkara apapun juga yang kamu telah dilarang darinya!
Wahai anakku..
Sesungguhnya Rabmu sangat dahsyat murka-Nya, siksa-Nya teramat pedih, maka hati-hatilah kamu wahai anakku, dan takutlah kamu terhadap kemurkaan-Nya, dan janganlah kamu terlena oleh kasih sayang Rabbmu dan sesungguhnya Allah menangguhkan (siksa-Nya) bagi orang yang berbuat dzalim, sampai-sampai jika Dia menyiksa orang tersebut, niscaya Dia tidak akan melepaskannya.
Wahai anakku...
Sesunguhnya di dalam ketaatan kepada Allah ada kelezatan dan kebahagiaan yang tidak akan dapat dirasakan kecuali dengan mencobanya.
Maka, wahai anakku...
Pergunakanlah ketaatan kepada Allah sebagai bahan ujian pada setiap harinya supaya engkau dapat merasakan kelezatan, dan supaya engkau dapat merasakan kebahagiaan ini, niscaya kamu dapat mengetahui keikhlasan dirku di dalam menasehatimu.
Wahai anakku..
Sesungguhnya engkau akan mendapati rasa berat hati di dalam ketaatan kepada Allah pada pertama kalinya, maka pikullah beban berat ini, dan bersabarlah padanya, sampai ketaatan tersebut engkau rasakan menjadi rutinitas yang dapat dijinakkan.
Wahai anakku...
Lihatlah kepada dirimu ketika dulu kamu berada di bangku (sekolah); kamu belajar membaca dan menulis, dan kamu diperintahkan supaya menghafal Al-Qur'anul Karim dengan mendiktekannya, bukankah kamu dulu di sana benci terhadap bangku (sekolah) serta gurunya, dan kamu berangan-angan supaya cepat berakhir? Nah, pada hari ini kamu telah mencapai kedudukan yang mana kamu dapat mengetahui faedah kesabaran dalam belajar di bangku (sekolah), dan engkau telah tahu bahwa pengajarmu dulu berusaha untuk kebaikan dirimu..
Maka, wahai anakku...
Dengarkanlah nasehatku, dan bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah sebagaimana engkau sabar dalam belajar di bangku (sekolah), niscaya nanti engkau akan mengetahui faedah dari nasehat ini, serta akan tampak jelas bagimu apabila hidayah telah membantu untuk beramal dengan nasehat ustadzmu.
Wahai anakku...
Janganlah kamu sekali-kali beranggapan bahwa bertakwa kepada Allah adalah shalat, puasa, dan semisalnya dari berbagai ibadah (yang dhahir) saja. Bahwa sesungguhnya bertakwa kepada Allah mencakup segala sesuatu, maka bertakwalah kamu kepada Allah pada (hak-hak) saudara-saudaramu, janganlah kamu sakiti salah seorang dari mereka, dan bertakwalah kamu kepada Allah pada (hak-hak) negerimu: Janganlah kamu khianati dia dan jangan kamu biarkan musuh menguasainya, serta bertakwalah kamu pada (hak-hak) dirimu, janganlah kamu sia-siakan waktu sehatmu dan janganlah kamu berperilaku kecuali perilaku yang mulia.
Wahai anakku..
Rasulullah saw telah bersabda: Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya (kebaikan tersebut) akan menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik
Wahai anakku...
Sesungguhnya Rabbmu mengetahui apa yang kamu betikkan dalam hatimu, dan Dia mengetahui apa yang engkau ucapkan dengan lisanmu, dan Dia melihat terhadap segala amalanmu, maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai anakku, dan berhati-hatilah kamu terhadap pengawasan-Nya pada saat kamu dalam keadaan yang tidak diridhai oleh-Nya.
Hati-hatilah kamu dari kemurkaan Rabbmu, yang mana Dialah yang telah menciptakanmu dan memberikan rizki kepadamu serta yang telah mengaruniai kamu akal yang dapat kamu gunakan di dalam kehidupanmu. Bagaimana perasaanmu ketika bapakmu melihat dirimu dalam keadaan melanggar perintahnya? Apakah kamu tidak khawatir nantinya bapakmu akan menghukummu? Maka jadikanlah perasaanmu sama seperti itu [bahkan lebih] kepada Allah, karena Dia dapat melihat dirimu disetiap kesempatan yang kamu tidak dapat melihat Dia! Maka janganlah kamu anggap enteng pada perkara apapun juga yang kamu telah dilarang darinya!
Wahai anakku..
Sesungguhnya Rabmu sangat dahsyat murka-Nya, siksa-Nya teramat pedih, maka hati-hatilah kamu wahai anakku, dan takutlah kamu terhadap kemurkaan-Nya, dan janganlah kamu terlena oleh kasih sayang Rabbmu dan sesungguhnya Allah menangguhkan (siksa-Nya) bagi orang yang berbuat dzalim, sampai-sampai jika Dia menyiksa orang tersebut, niscaya Dia tidak akan melepaskannya.
Wahai anakku...
Sesunguhnya di dalam ketaatan kepada Allah ada kelezatan dan kebahagiaan yang tidak akan dapat dirasakan kecuali dengan mencobanya.
Maka, wahai anakku...
Pergunakanlah ketaatan kepada Allah sebagai bahan ujian pada setiap harinya supaya engkau dapat merasakan kelezatan, dan supaya engkau dapat merasakan kebahagiaan ini, niscaya kamu dapat mengetahui keikhlasan dirku di dalam menasehatimu.
Wahai anakku..
Sesungguhnya engkau akan mendapati rasa berat hati di dalam ketaatan kepada Allah pada pertama kalinya, maka pikullah beban berat ini, dan bersabarlah padanya, sampai ketaatan tersebut engkau rasakan menjadi rutinitas yang dapat dijinakkan.
Wahai anakku...
Lihatlah kepada dirimu ketika dulu kamu berada di bangku (sekolah); kamu belajar membaca dan menulis, dan kamu diperintahkan supaya menghafal Al-Qur'anul Karim dengan mendiktekannya, bukankah kamu dulu di sana benci terhadap bangku (sekolah) serta gurunya, dan kamu berangan-angan supaya cepat berakhir? Nah, pada hari ini kamu telah mencapai kedudukan yang mana kamu dapat mengetahui faedah kesabaran dalam belajar di bangku (sekolah), dan engkau telah tahu bahwa pengajarmu dulu berusaha untuk kebaikan dirimu..
Maka, wahai anakku...
Dengarkanlah nasehatku, dan bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah sebagaimana engkau sabar dalam belajar di bangku (sekolah), niscaya nanti engkau akan mengetahui faedah dari nasehat ini, serta akan tampak jelas bagimu apabila hidayah telah membantu untuk beramal dengan nasehat ustadzmu.
Wahai anakku...
Janganlah kamu sekali-kali beranggapan bahwa bertakwa kepada Allah adalah shalat, puasa, dan semisalnya dari berbagai ibadah (yang dhahir) saja. Bahwa sesungguhnya bertakwa kepada Allah mencakup segala sesuatu, maka bertakwalah kamu kepada Allah pada (hak-hak) saudara-saudaramu, janganlah kamu sakiti salah seorang dari mereka, dan bertakwalah kamu kepada Allah pada (hak-hak) negerimu: Janganlah kamu khianati dia dan jangan kamu biarkan musuh menguasainya, serta bertakwalah kamu pada (hak-hak) dirimu, janganlah kamu sia-siakan waktu sehatmu dan janganlah kamu berperilaku kecuali perilaku yang mulia.
Wahai anakku..
Rasulullah saw telah bersabda: Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya (kebaikan tersebut) akan menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik
Minggu, 15 Agustus 2010
MENGINGAT MATI
Rasulullah saw. bersabda, ''Ingatlah kematian. Demi Zat yang nyawaku berada dalam kekuasaan-Nya, kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis.''
Ada seorang teman yang sangat rajin beribadah. Shalatnya tak lepas dari linang air mata, tahajud tak pernah putus, bahkan anak dan istrinya pun diajak pula berjamaah di masjid. Selidik punya selidik, ternyata saat itu dia sedang menanggung utang. Di antara ibadah-ibadahnya itu dia selipkan doa-doa agar utangnya segera terlunasi. Selang beberapa lama, Allah Azza wa Jalla, Zat yang Mahakaya pun berkenan melunasi utang teman tersebut. Sayangnya, begitu utang terlunasi doanya mulai jarang, hilang pula motivasinya untuk beribadah. Biasanya kalau kehilangan shalat tahajud ia sedih bukan main. Tapi, lama-kelamaan tahajud tertinggal justru menjadi senang karena jadwal tidur menjadi cukup. Bahkan sebelum azan biasanya sudah menuju mesjid, tapi akhir-akhir ini datang ke mesjid justru ketika azan. Hari berikutnya ketika azan tuntas baru selesai wudhu. Lain lagi pada besok harinya, ketika azan selesai justru masih di rumah, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk shalat di rumah.
Begitu pun untuk shalat sunah, biasanya ketika masuk masjid shalat sunah tahiyatul masjid terlebih dulu dan salat fardhu pun selalu dibarengi shalat rawatib. Tapi sekarang saat datang lebih awal pun malah pura-pura berdiri menunggu iqamat, selalu ada saja alasannya. Sesudah iqamat biasanya memburu shaf paling awal, kini yang diburu justru shaf paling tengah, hari berikutnya ia memilih shaf sebelah pojok, bahkan lama-lama mencari shaf di dekat pintu, dengan alasan supaya tidak terlambat dua kali. Saat akan shalat sunah rawatib, ia malah menundanya dengan alasan nanti akan di rumah saja, padahal ketika sampai di rumah pun tidak dikerjakan. Entah disadari atau tidak oleh dirinya, ternyata pelan-pelan banyak ibadah yang ditinggalkan. Bahkan pergi ke majelis taklim yang biasanya rutin dilakukan, majelis ilmu di mana saja dikejar, sayangnya akhir-akhir ini kebiasaan itu malah hilang.
Ketika zikir pun biasanya selalu dihayati, sekarang justru antara apa yang diucapkan di mulut dengan suasana hati, sama sekali bak gayung tak bersambut. Mulut mengucap, tapi hati keliling dunia, masyaallah. Sudah dilakukan tanpa kesadaran, seringkali pula selalu ada alasan untuk tidak melakukannya. Saat-saat berdoa pun menjadi kering, tidak lagi memancarkan kekuatan ruhiah, tidak ada sentuhan, inilah tanda-tanda hati mulai mengeras.
Para ikhwan dan akhwat, sahalus-halus kehinaan di sisi Allah adalah tercerabutnya kedekatan kita dari sisi-Nya. Hal ini biasanya ditandai dengan kualitas ibadah yang jauh dari meningkat, atau bahkan malah menurun. Tidak bertambah bagus ibadahnya, tidak bertambah pula ilmu yang dapat membuatnya takut kepada Allah, bahkan justru maksiat pun sudah mulai dilakukan, bahkan yang bersangkutan tidak merasa rugi. Inilah tanda-tanda akan tercerabutnya nikmat berdekatan bersama Allah Azza wa Jalla. Pantaslah bila Imam Ibnu Athaillah pernah berujar, ''Rontoknya iman ini akan terjadi pelan-pelan, terkikis-kikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya tanpa terasa habis tanpa tersisa.'' Demikianlah yang terjadi bagi orang yang tidak berusaha memelihara iman di dalam kalbunya. Karenanya jangan pernah permainkan nikmat iman di hati ini.
Kalau ibadah sudah tercerabut satu persatu, maka inilah tanda mulai tercerabutnya hidayah dari-Nya. Akibat selanjutnya mudah ditebak, ketahanan penjagaan diri menjadi blong, kata-katanya menjadi kasar, mata jelalatan tidak terkendali, dan emosinya pun mudah membara. Apalagi ketika ibadah shalat yang merupakan benteng dari perbuatan keji dan munkar mulai lambat dilakukan, kadang-kadang pula mulai ditinggalkan. Ibadah yang lain nasibnya tak jauh beda, hingga akhirnya meningallah ia dalam keadaan hilang keyakinannya kepada Allah. Inilah yang disebut su'ul khatimah (jelek di akhir), naudzzubillah. Apalah artinya hidup kalau berakhir tragis seperti ini.
Bila kita merenungi kisah di atas, nampaklah bahwa salah satu hikmah yang dapat diambil darinya adalah jika kita sedang berbuat kurang bermanfaat bahkan zalim, maka salah satu teknik mengeremnya adalah mengingat mati. Bagaimana kalau tiba-tiba kita mati, padahal kita sedang maksiat? Tidak takutkah kita mati suul khatimah?. Ternyata ingat mati menjadi bagian yang sangat penting setelah doa dan ikhtiar dalam memelihara iman di hati. Rasulullah saw telah mengingatkan para sahabatnya untuk selalu mengingat kematian. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah saw ke luar menuju masjid. Tiba-tiba beliau mendapati suatu kaum yang sedang tertawa-tawa. Maka beliau bersabda, ''Ingatlah kematian. Demi Zat yang nyawaku berada dalam kekuasaan-Nya, kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis.''
Mengingat mati akan membuat kita seakan punya rem dari berbuat dosa. Akibatnya di mana saja dan kapan saja kita akan senantiasa terarahkan untuk melakukan segala sesuatu hanya yang bermanfaat. Kalau kita melihat para arifin dan salafus shalih, mengingat mati bagi mereka, seumpama seorang pemuda yang menunggu kekasihnya. Di mana seorang kekasih tidak pernah melupakan janji kekasihnya. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ra bahwa ketika kematian menjemputnya ia berkata, ''Kekasih datang dalam keadaan miskin. Tiadalah beruntung siapa yang menyesali kedatangannya. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa kefakiran lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan kematian lebih aku sukai daripada kehidupan, maka mudahkanlah bagiku kematian sehingga aku menemui-Mu.'' Semoga kita digolongkan Allah SWT menjadi orang yang memperoleh karunia khusnul khatimah. Aamiin Allaahumma Aamiin
Ada seorang teman yang sangat rajin beribadah. Shalatnya tak lepas dari linang air mata, tahajud tak pernah putus, bahkan anak dan istrinya pun diajak pula berjamaah di masjid. Selidik punya selidik, ternyata saat itu dia sedang menanggung utang. Di antara ibadah-ibadahnya itu dia selipkan doa-doa agar utangnya segera terlunasi. Selang beberapa lama, Allah Azza wa Jalla, Zat yang Mahakaya pun berkenan melunasi utang teman tersebut. Sayangnya, begitu utang terlunasi doanya mulai jarang, hilang pula motivasinya untuk beribadah. Biasanya kalau kehilangan shalat tahajud ia sedih bukan main. Tapi, lama-kelamaan tahajud tertinggal justru menjadi senang karena jadwal tidur menjadi cukup. Bahkan sebelum azan biasanya sudah menuju mesjid, tapi akhir-akhir ini datang ke mesjid justru ketika azan. Hari berikutnya ketika azan tuntas baru selesai wudhu. Lain lagi pada besok harinya, ketika azan selesai justru masih di rumah, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk shalat di rumah.
Begitu pun untuk shalat sunah, biasanya ketika masuk masjid shalat sunah tahiyatul masjid terlebih dulu dan salat fardhu pun selalu dibarengi shalat rawatib. Tapi sekarang saat datang lebih awal pun malah pura-pura berdiri menunggu iqamat, selalu ada saja alasannya. Sesudah iqamat biasanya memburu shaf paling awal, kini yang diburu justru shaf paling tengah, hari berikutnya ia memilih shaf sebelah pojok, bahkan lama-lama mencari shaf di dekat pintu, dengan alasan supaya tidak terlambat dua kali. Saat akan shalat sunah rawatib, ia malah menundanya dengan alasan nanti akan di rumah saja, padahal ketika sampai di rumah pun tidak dikerjakan. Entah disadari atau tidak oleh dirinya, ternyata pelan-pelan banyak ibadah yang ditinggalkan. Bahkan pergi ke majelis taklim yang biasanya rutin dilakukan, majelis ilmu di mana saja dikejar, sayangnya akhir-akhir ini kebiasaan itu malah hilang.
Ketika zikir pun biasanya selalu dihayati, sekarang justru antara apa yang diucapkan di mulut dengan suasana hati, sama sekali bak gayung tak bersambut. Mulut mengucap, tapi hati keliling dunia, masyaallah. Sudah dilakukan tanpa kesadaran, seringkali pula selalu ada alasan untuk tidak melakukannya. Saat-saat berdoa pun menjadi kering, tidak lagi memancarkan kekuatan ruhiah, tidak ada sentuhan, inilah tanda-tanda hati mulai mengeras.
Para ikhwan dan akhwat, sahalus-halus kehinaan di sisi Allah adalah tercerabutnya kedekatan kita dari sisi-Nya. Hal ini biasanya ditandai dengan kualitas ibadah yang jauh dari meningkat, atau bahkan malah menurun. Tidak bertambah bagus ibadahnya, tidak bertambah pula ilmu yang dapat membuatnya takut kepada Allah, bahkan justru maksiat pun sudah mulai dilakukan, bahkan yang bersangkutan tidak merasa rugi. Inilah tanda-tanda akan tercerabutnya nikmat berdekatan bersama Allah Azza wa Jalla. Pantaslah bila Imam Ibnu Athaillah pernah berujar, ''Rontoknya iman ini akan terjadi pelan-pelan, terkikis-kikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya tanpa terasa habis tanpa tersisa.'' Demikianlah yang terjadi bagi orang yang tidak berusaha memelihara iman di dalam kalbunya. Karenanya jangan pernah permainkan nikmat iman di hati ini.
Kalau ibadah sudah tercerabut satu persatu, maka inilah tanda mulai tercerabutnya hidayah dari-Nya. Akibat selanjutnya mudah ditebak, ketahanan penjagaan diri menjadi blong, kata-katanya menjadi kasar, mata jelalatan tidak terkendali, dan emosinya pun mudah membara. Apalagi ketika ibadah shalat yang merupakan benteng dari perbuatan keji dan munkar mulai lambat dilakukan, kadang-kadang pula mulai ditinggalkan. Ibadah yang lain nasibnya tak jauh beda, hingga akhirnya meningallah ia dalam keadaan hilang keyakinannya kepada Allah. Inilah yang disebut su'ul khatimah (jelek di akhir), naudzzubillah. Apalah artinya hidup kalau berakhir tragis seperti ini.
Bila kita merenungi kisah di atas, nampaklah bahwa salah satu hikmah yang dapat diambil darinya adalah jika kita sedang berbuat kurang bermanfaat bahkan zalim, maka salah satu teknik mengeremnya adalah mengingat mati. Bagaimana kalau tiba-tiba kita mati, padahal kita sedang maksiat? Tidak takutkah kita mati suul khatimah?. Ternyata ingat mati menjadi bagian yang sangat penting setelah doa dan ikhtiar dalam memelihara iman di hati. Rasulullah saw telah mengingatkan para sahabatnya untuk selalu mengingat kematian. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah saw ke luar menuju masjid. Tiba-tiba beliau mendapati suatu kaum yang sedang tertawa-tawa. Maka beliau bersabda, ''Ingatlah kematian. Demi Zat yang nyawaku berada dalam kekuasaan-Nya, kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis.''
Mengingat mati akan membuat kita seakan punya rem dari berbuat dosa. Akibatnya di mana saja dan kapan saja kita akan senantiasa terarahkan untuk melakukan segala sesuatu hanya yang bermanfaat. Kalau kita melihat para arifin dan salafus shalih, mengingat mati bagi mereka, seumpama seorang pemuda yang menunggu kekasihnya. Di mana seorang kekasih tidak pernah melupakan janji kekasihnya. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ra bahwa ketika kematian menjemputnya ia berkata, ''Kekasih datang dalam keadaan miskin. Tiadalah beruntung siapa yang menyesali kedatangannya. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa kefakiran lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan kematian lebih aku sukai daripada kehidupan, maka mudahkanlah bagiku kematian sehingga aku menemui-Mu.'' Semoga kita digolongkan Allah SWT menjadi orang yang memperoleh karunia khusnul khatimah. Aamiin Allaahumma Aamiin
TEKNIK MELAKUKAN ROBITHOH
Di dalam shalat, ketika melakukan tasyahud, kita diperintahkan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Assalamu’alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh (salam dan rahmat serta barakah Allah untukmu wahai Nabi SAW). Perintah ini harus dilakukan secara lahir dan batin, secara lahir dengan mengucapkan salam itu sendiri, sedangkan secara batin adalah menghubungkan rohani kita dengan rohani Rasul SAW, agar kita bisa bersama dengan Beliau SAW.
Bersama dengan Rasul SAW sekaligus mengandung makna bersama dengan Allah SWT karena Rasul SAW tidak pernah berpisah sedetik-pun dari-Nya. Kenyataan bahwa di dalam rohani Beliau SAW tersimpan Nur Allah SWT, dan bahwa Beliau SAW sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah ra. selalu berdzikir kepada Allah SWT dalam setiap detik yang Beliau SAW miliki (kana yadzkurullaha fi kulli ahyanihi) [Musnad Abi Ya’la, juz VIII: 355] merupakan indikasi nyata atas makna ini.
Dalam kaitan inilah mengapa sebagian Kaum Arifin yaitu orang-orang yang sudah mengenal Allah SWT secara tahkik berkata:
"Bersamalah engkau selalu dengan Allah, dan jika engkau belum bisa, maka bersamalah engkau selalu dengan orang yang sudah bersama dengan Allah" [Tanwir al-Qulub, hal. 512].
Namun begitu, karena kita tidak mengenal Rasul SAW secara jasmani, maka yang dapat kita lakukan adalah menghubungkan rohani kita dengan rohani ulama yang kita kenal secara jasmani, yaitu ulama yang benar-benar berkapasitas sebagai Waratsah al-Anbiya (Ahli Waris Para Nabi), yang kepada mereka beliau mewariskan isi rohani beliau dengan izin Allah SWT.
Hamba-hamba Allah SWT seperti itu dalam al-Quran disebut antara lain dengan al-Shadiqun, dan Allah memerintahkan kita agar selalu bersama dengan mereka (secara jasmani dan rohani).
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. al-Taubah : 119).
Firman Allah di atas dijelaskan oleh Imam al-Baidhawi dalam Tafsir-nya dengan ungkapan:
"(Hendaklah kamu bersama dengan mereka) dalam keimanan dan janji-janji mereka, atau dalam agama Allah dari segi niat, perkataan, dan perbuatan." [Tafsir al-Baydhawi, juz III: 178].
Penjelasan senada dikemukakan oleh Imam al-Alusi dalam Ruh al-Maani-nya [Ruh al-Ma’ani,juz XI: 45], dan juga oleh Imam Abu Saud dalam Tafsir-nya Irsyad al-Aql al-Salim ila Mazaya al-Quran al-Karim dengan redaksi yang lebih gamblang:
"(Hendaklah kamu bersama dengan mereka) dalam keimanan dan janji-janji mereka, atau dalam agama Allah dari segi niat, perkataan, dan perbuatan, atau dalam semua urusan." [Tafsir Abi al-Sa’ud, juz IV: 110].
Artinya, bersama atau berjamaah dengan orang-orang yang benar itu dilakukan dalam semua keadaan dan dalam semua persoalan, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Bahkan, bersama atau berjamaah secara rohani jauh lebih mungkin direalisasikan daripada berjamaah secara jasmani, sebab tidak mungkin kita dapat berjamaah dengan mereka secara jasmani dalam semua keadaan. Maka al-Shadiqun yaitu orang-orang yang benar, dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka kepada Allah, sehingga sebutan lain yang dikemukakan al-Quran untuk mereka adalah al-Muminuna Haqqan, orang-orang mukmin sejati (hak), yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah SWT, hati mereka bergetar dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka keimanan mereka semakin bertambah, dan hanya kepada Allah SWT mereka bertawakal, menegakkan shalat dan menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepada mereka [Al-Anfal, 8: 3-5]; bukan orang-orang yang beriman tetapi di dalam hatinya tumbuh subur sifat-sifat nifaq (munafik) yang diantara ciri-ciri utama mereka adalah bahwa mereka tidak berdzikir kepada Allah kecuali sedikit [Al-Nisa' : 142].
Mereka tiada lain adalah wali-wali Allah yang oleh Nabi sebagaimana disinggung sebelumnya disebut dengan Mafatih al-Dzikr ‘kunci-kunci dzikir’, dan yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kaum sufi, dan oleh Ibn Taimiyah disebut sebagai golongan yang paling baik setelah Nabi. [Majmu’ al-Fatawa, juz XI: 17]. Memandang mereka melahirkan dzikir kata Nabi dalam riwayat Imam al-Thabrani ketika menggambarkan keberadaan mereka [Al-Mu’jam al-Kabir, juz X: 205]. Memandang mereka, terutama yang dilakukan secara rohani, mewujudkan apa yang dimaksud dengan rabithah di sini.
Bersama dengan Rasul SAW sekaligus mengandung makna bersama dengan Allah SWT karena Rasul SAW tidak pernah berpisah sedetik-pun dari-Nya. Kenyataan bahwa di dalam rohani Beliau SAW tersimpan Nur Allah SWT, dan bahwa Beliau SAW sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah ra. selalu berdzikir kepada Allah SWT dalam setiap detik yang Beliau SAW miliki (kana yadzkurullaha fi kulli ahyanihi) [Musnad Abi Ya’la, juz VIII: 355] merupakan indikasi nyata atas makna ini.
Dalam kaitan inilah mengapa sebagian Kaum Arifin yaitu orang-orang yang sudah mengenal Allah SWT secara tahkik berkata:
"Bersamalah engkau selalu dengan Allah, dan jika engkau belum bisa, maka bersamalah engkau selalu dengan orang yang sudah bersama dengan Allah" [Tanwir al-Qulub, hal. 512].
Namun begitu, karena kita tidak mengenal Rasul SAW secara jasmani, maka yang dapat kita lakukan adalah menghubungkan rohani kita dengan rohani ulama yang kita kenal secara jasmani, yaitu ulama yang benar-benar berkapasitas sebagai Waratsah al-Anbiya (Ahli Waris Para Nabi), yang kepada mereka beliau mewariskan isi rohani beliau dengan izin Allah SWT.
Hamba-hamba Allah SWT seperti itu dalam al-Quran disebut antara lain dengan al-Shadiqun, dan Allah memerintahkan kita agar selalu bersama dengan mereka (secara jasmani dan rohani).
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. al-Taubah : 119).
Firman Allah di atas dijelaskan oleh Imam al-Baidhawi dalam Tafsir-nya dengan ungkapan:
"(Hendaklah kamu bersama dengan mereka) dalam keimanan dan janji-janji mereka, atau dalam agama Allah dari segi niat, perkataan, dan perbuatan." [Tafsir al-Baydhawi, juz III: 178].
Penjelasan senada dikemukakan oleh Imam al-Alusi dalam Ruh al-Maani-nya [Ruh al-Ma’ani,juz XI: 45], dan juga oleh Imam Abu Saud dalam Tafsir-nya Irsyad al-Aql al-Salim ila Mazaya al-Quran al-Karim dengan redaksi yang lebih gamblang:
"(Hendaklah kamu bersama dengan mereka) dalam keimanan dan janji-janji mereka, atau dalam agama Allah dari segi niat, perkataan, dan perbuatan, atau dalam semua urusan." [Tafsir Abi al-Sa’ud, juz IV: 110].
Artinya, bersama atau berjamaah dengan orang-orang yang benar itu dilakukan dalam semua keadaan dan dalam semua persoalan, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Bahkan, bersama atau berjamaah secara rohani jauh lebih mungkin direalisasikan daripada berjamaah secara jasmani, sebab tidak mungkin kita dapat berjamaah dengan mereka secara jasmani dalam semua keadaan. Maka al-Shadiqun yaitu orang-orang yang benar, dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka kepada Allah, sehingga sebutan lain yang dikemukakan al-Quran untuk mereka adalah al-Muminuna Haqqan, orang-orang mukmin sejati (hak), yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah SWT, hati mereka bergetar dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka keimanan mereka semakin bertambah, dan hanya kepada Allah SWT mereka bertawakal, menegakkan shalat dan menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepada mereka [Al-Anfal, 8: 3-5]; bukan orang-orang yang beriman tetapi di dalam hatinya tumbuh subur sifat-sifat nifaq (munafik) yang diantara ciri-ciri utama mereka adalah bahwa mereka tidak berdzikir kepada Allah kecuali sedikit [Al-Nisa' : 142].
Mereka tiada lain adalah wali-wali Allah yang oleh Nabi sebagaimana disinggung sebelumnya disebut dengan Mafatih al-Dzikr ‘kunci-kunci dzikir’, dan yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kaum sufi, dan oleh Ibn Taimiyah disebut sebagai golongan yang paling baik setelah Nabi. [Majmu’ al-Fatawa, juz XI: 17]. Memandang mereka melahirkan dzikir kata Nabi dalam riwayat Imam al-Thabrani ketika menggambarkan keberadaan mereka [Al-Mu’jam al-Kabir, juz X: 205]. Memandang mereka, terutama yang dilakukan secara rohani, mewujudkan apa yang dimaksud dengan rabithah di sini.
SULUK DALAM PANDANGAN IBNU TAIMIYAH
Ibn Taimiyah yang selama ini dituding sebagai anti thariqah ternyata justru sangat mendukung suluk sebagai unsur fundamental dalam thariqah. Dalam kaitan ini beliau menegaskan dalam Majmu' al-Fatawa-nya:
Suluk adalah menempuh jalan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa realisasi akidah, ibadah, akhlak.
Semua ini sangat jelas dalam ibadah al-Quran dan al-Sunnah, karena suluk menempati posisi makanan yang merupakan keharusan bagi orang mukmin. Oleh karena itu, semua sahabat mengenal suluk dengan petunjuk al-Quran dan al-Sunnah dan sekaligus dari penyampaian Rasul sendiri; mereka dalam hal itu tidak membutuhkan ahli-ahli fikih dari kalangan sahabat, dan mereka pun dalam hal itu tidak pernah saling bertentangan satu sama lain, sebagaimana mereka saling bertentangan dalam kasus-kasus fikih yang pengetahuan tentang kasus-kasus ini tertutup bagi kebanyakan sahabat, sehingga mereka berbicara dalam fatwa-fatwa yang diminta oleh suatu kelompok dalam kasus-kasus itu.
Adapun (suluk) yang dilakukan oleh orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan mengintensifkan ibadah yang diwajibkan dan ibadah yang disunnahkan, maka masing-masing dari mereka berpedoman kepada al-Quran dan al-Sunnah, karena al-Quran dan al-Hadis sarat dengan hal ini. Dan jika salah seorang dari mereka dalam hal itu berbicara dengan perkataan yang tidak ia sandarkan kepada dirinya sendiri, maka perkataan itu atau maknanya disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya; kadang-kadang di antara mereka ada yang mengucapkan kata-kata hikmah, dan hal itu ternyata berasal dari Nabi saw sendiri; ini sama dengan kata-kata hikmah, yang dikatakan orang dalam menafsirkan firman Allah nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya' [Majmu' al-Fatawa, juz XIX: 273].
Lebih jauh Ibn Taimiyah menegaskan bahwa masalah suluk merupakan bagian dari masalah akidah yang semuanya ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah sehingga tidak layak dipertentangkan:
Masalah suluk merupakan salah satu jenis masalah akidah; semuanya ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah...Mereka (para sahabat) tidak pernah saling bertentangan dalam masalah akidah dan tidak pula dalam masalah thariqah 'jalan' menuju Allah yang dengannya seseorang dapat menjadi salah seorang wali dari wali wali Allah yang abrar 'bebas dari noda durhaka' dan muqarrabin' didekatkan kepada Allah'. Oleh karena itu, syekh-syekh tarekat sufi jika mereka memerlukan rujukan dalam perkara-perkara syariat seperti yang berkenaan dengan nikah, warisan, bersuci, sujud sahwi, dan yang semacamnya, mereka mengikuti (taklid) ahli-ahli fikih...berijtihad; dan barangsiapa di antara mereka mengikuti Rasul, maka ia benar; dan barangsiapa menyimpang dari Rasul, maka ia salah [Majmu' al-Fatawa juz XIX: 274].
Jadi, dalam pandangan Ibn Taimiyah, sebuah pandangan yang sangat ideal, suluk merupakan masalah akidah sehingga tidak dapat didekati dengan pendekatan fikih, atau merupakan realisasi konkret dari tasawuf yang oleh Imam Muhammad Ibn Ahmad bin Jazi al-Kalabi al-Gharnathi disebut sebagai fikih batin [al-Qawanin al-Fiqhiyyah li Ibn Jazi, hal. 277].
Hal-hal yang berkenaan dengan suluk semuanya didasarkan pada al-Quran dan al-Sunnah. Khalwat Nabi saw di Gua Hira', khususnya, menjadi rujukan utama bagi para salik sebagaimana ditegaskan juga oleh Buya Hamka ketika ia mengatakan:
Maka kaum Shufiyah yang mensucikan dirinya dalam khalwatnya itu, pun mengambillah contoh teladan atas amal-amal mereka dalam khalwat, suluk dan tariqat, dan bermacam-macam sistem yang lain: khalawat dan tahannust Nabi di Gua Hira', sampai terbuka hijab kegaiban oleh kemurnian jiwa [Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, hal. 23].
Melalui suluk yang memenuhi syarat dan rukunnya seseorang dengan izin Tuhannya akan mencapai tauhid yang murni atau mengalami Tuhan secara haqq al-yaqin 'keyakinan yang hak yang tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun', sehingga tidak lagi memerlukan argumentasi-argumentasi logis mengenai keberadaan dan keesaan-Nya; ia sudah mendapatkan pancaran cahaya langsung dari Tuhan sehingga ia pun berjalan di muka bumi bagaikan pelita yang menerangi sekelilingnya. Pelita mereka berasal dari nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya', yang oleh Ibn al-Qayyin sambil mengutip firman Tuhan dalam ayat ke 35 dari surah al-Nur digambarkan dengan ungkapan:
Lampu-lampu seseorang yang 'mengalami' Tuhan secara tahkik (muwahhid) dan yang berjalan (salik) di atas jalan dan thariqah Rasul menyala dan bersinar dari pohon yang diberkati, pohon zaitun yang tidak tumbuh di Timur dan tidak pula di Barat; yang minyaknya sudah hampir bisa menerangi tidak disentuh api; nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya'; Allah membimbing kepada cahaya-Nya orang-orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia [Madarij al-Salikin, juz III: 98].
Suluk, Realisasi Khalwat, 'Uzlah dan I'tikaf
Dalam tarekat sufi suluk dipahami dan diwujudkan dalam bentuk khalwat dan 'uzlah, yaitu mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu (10, 20, atau 40 hari) di sebuah tempat yang bebas dari kebisingan dan hiruk pikuk duniawi.
Teladan yang diambil oleh para salik dalam hal ini seperti ditegaskan Buya Hamka adalah kegemaran Nabi melakukan khalwat dan tahannuts di Gua Hira'. Imam al-Bukhari dan Muslim serta beberapa imam hadis lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa umm al-mu'min Aisyah berkata:
Nabi digemarkan oleh Allah untuk melakukan khalwat, beliau selalu berkhalwat di Gua Hira' dan melakukan tahannuts di sana, yaitu beribadah selama beberapa malam tertentu [Shahih al-Bukhari, juz I: 4; Shahih Muslim, juz I: 140; Shahih Ibn Hibban, juz I: 216; Musnad Ahmad, juz VI: 232].
Para sufi melakukan suluk di masjid-masjid atau surau-surau yang oleh al-Quran disebut sebagai rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk dimuliakan dan dijadikan tempat berdzikir menyebut asma-Nya [Al-Nur :36]. Rumah-rumah semacam inilah yang oleh para salik dijadikan tempat khalwat dan 'uzlah; mereka menetap disitu selama beberapa hari untuk melakukan ibadah dan dzikir secara intensif. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila suluk mereka disebut juga dengan I'tikaf yang dari segi bahasa bermakna berdiam di sebuah tempat selama jangka waktu tertentu.
Dalam kasus ini para salik merujuk kepada I'tikaf Nabi SAW selama sepuluh hari dalam bulan Ramadhan. Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa 'Aisyah ra. berkata:
Nabi SAW selalu I'tikaf selama sepuluh hari terakhir dari bulan bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau [Shahih al-Bukhari, juz II: 213; Shahih Muslim, juz II: 831].
Namun begitu, sebagaimana diceritakan oleh Abu Dzar al-Ghiffari, tidak jarang pula Nabi melakukan I'tikaf sepuluh hari pertama dan kadang-kadang sepuluh hari ke dua atau pertengahan dari bulan Ramadhan [Shahih al-Bukhari, juz II: 713; Shahih Muslim, juz II: 825].
Dan satu yang barangkali penting digarisbawahi di sini adalah bahwa I'tikaf pada dasarnya merupakan ibadah tersendiri; artinya tidak harus terkait dengan keharusan berpuasa dan tidak harus pula terkait dengan bulan Ramadhan. Imam al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn. Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:
Tidak ada keharusan berpuasa atas orang yang beri'tikaf kecuali ia menetapkan puasa itu untuk dirinya sendiri [Al-Mustadrak, juz I: 605; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, juz IV: 318; Sunan Daruquthi, juz II: 199]. Imam al-Baihaqi dan beberapa Imam hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa ia berkata:
Nabi SAW pernah melakukan I'tikaf selama sepuluh hari pertama bulan syawal [Sunan al-Baihaqi al-Kubra, juz IV: 318; Sunan Abi Dawud, juz II: 331; al-Sunan al-Kubra, juz II: 260].
Ibn al-Qayyim mengutip pendapat ulama yang mendukung keabsahan I'tikaf sebagai ibadah yang mandiri ketika ia mengatakan:
I'tikaf merupakan ibadah yang berdiri sendiri, sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya ibadah-ibadah lainnya seperti haji, salat, jihad dan ribath (merabit); I'tikaf adalah menetap di suatu tempat tertentu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya ribath (merabit); dan I'tifaf merupakan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) itu sendiri sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya haji [Hasyiyah Ibn al-Qayyim, juz VII: 106].
Satu hal yang pasti adalah bahwa suluk yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah SWT akan melahirkan manusia baru yang dari dalam hatinya memancar mata air dan sumber-sumber hikmah yang kemudian mengalir pada lisannya sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah:
Tidaklah seorang hamba mengikhlaskan dirinya selama empat puluh pagi (hari) kecuali dari kalbunya memancar sumber-sumber hikmah yang mengalir pada lisannya [Mushannaf Ibn Abi Syaibah, juz VII: 80; Musnad al-Syihab, juz I: 285].
Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa suluk dapat membidani kelahiran manusia baru yang utuh sehingga layak dijadikan sarana pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan yang selama ini lebih banyak menjadi slogan daripada kenyataan.
Suluk adalah menempuh jalan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa realisasi akidah, ibadah, akhlak.
Semua ini sangat jelas dalam ibadah al-Quran dan al-Sunnah, karena suluk menempati posisi makanan yang merupakan keharusan bagi orang mukmin. Oleh karena itu, semua sahabat mengenal suluk dengan petunjuk al-Quran dan al-Sunnah dan sekaligus dari penyampaian Rasul sendiri; mereka dalam hal itu tidak membutuhkan ahli-ahli fikih dari kalangan sahabat, dan mereka pun dalam hal itu tidak pernah saling bertentangan satu sama lain, sebagaimana mereka saling bertentangan dalam kasus-kasus fikih yang pengetahuan tentang kasus-kasus ini tertutup bagi kebanyakan sahabat, sehingga mereka berbicara dalam fatwa-fatwa yang diminta oleh suatu kelompok dalam kasus-kasus itu.
Adapun (suluk) yang dilakukan oleh orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan mengintensifkan ibadah yang diwajibkan dan ibadah yang disunnahkan, maka masing-masing dari mereka berpedoman kepada al-Quran dan al-Sunnah, karena al-Quran dan al-Hadis sarat dengan hal ini. Dan jika salah seorang dari mereka dalam hal itu berbicara dengan perkataan yang tidak ia sandarkan kepada dirinya sendiri, maka perkataan itu atau maknanya disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya; kadang-kadang di antara mereka ada yang mengucapkan kata-kata hikmah, dan hal itu ternyata berasal dari Nabi saw sendiri; ini sama dengan kata-kata hikmah, yang dikatakan orang dalam menafsirkan firman Allah nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya' [Majmu' al-Fatawa, juz XIX: 273].
Lebih jauh Ibn Taimiyah menegaskan bahwa masalah suluk merupakan bagian dari masalah akidah yang semuanya ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah sehingga tidak layak dipertentangkan:
Masalah suluk merupakan salah satu jenis masalah akidah; semuanya ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah...Mereka (para sahabat) tidak pernah saling bertentangan dalam masalah akidah dan tidak pula dalam masalah thariqah 'jalan' menuju Allah yang dengannya seseorang dapat menjadi salah seorang wali dari wali wali Allah yang abrar 'bebas dari noda durhaka' dan muqarrabin' didekatkan kepada Allah'. Oleh karena itu, syekh-syekh tarekat sufi jika mereka memerlukan rujukan dalam perkara-perkara syariat seperti yang berkenaan dengan nikah, warisan, bersuci, sujud sahwi, dan yang semacamnya, mereka mengikuti (taklid) ahli-ahli fikih...berijtihad; dan barangsiapa di antara mereka mengikuti Rasul, maka ia benar; dan barangsiapa menyimpang dari Rasul, maka ia salah [Majmu' al-Fatawa juz XIX: 274].
Jadi, dalam pandangan Ibn Taimiyah, sebuah pandangan yang sangat ideal, suluk merupakan masalah akidah sehingga tidak dapat didekati dengan pendekatan fikih, atau merupakan realisasi konkret dari tasawuf yang oleh Imam Muhammad Ibn Ahmad bin Jazi al-Kalabi al-Gharnathi disebut sebagai fikih batin [al-Qawanin al-Fiqhiyyah li Ibn Jazi, hal. 277].
Hal-hal yang berkenaan dengan suluk semuanya didasarkan pada al-Quran dan al-Sunnah. Khalwat Nabi saw di Gua Hira', khususnya, menjadi rujukan utama bagi para salik sebagaimana ditegaskan juga oleh Buya Hamka ketika ia mengatakan:
Maka kaum Shufiyah yang mensucikan dirinya dalam khalwatnya itu, pun mengambillah contoh teladan atas amal-amal mereka dalam khalwat, suluk dan tariqat, dan bermacam-macam sistem yang lain: khalawat dan tahannust Nabi di Gua Hira', sampai terbuka hijab kegaiban oleh kemurnian jiwa [Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, hal. 23].
Melalui suluk yang memenuhi syarat dan rukunnya seseorang dengan izin Tuhannya akan mencapai tauhid yang murni atau mengalami Tuhan secara haqq al-yaqin 'keyakinan yang hak yang tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun', sehingga tidak lagi memerlukan argumentasi-argumentasi logis mengenai keberadaan dan keesaan-Nya; ia sudah mendapatkan pancaran cahaya langsung dari Tuhan sehingga ia pun berjalan di muka bumi bagaikan pelita yang menerangi sekelilingnya. Pelita mereka berasal dari nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya', yang oleh Ibn al-Qayyin sambil mengutip firman Tuhan dalam ayat ke 35 dari surah al-Nur digambarkan dengan ungkapan:
Lampu-lampu seseorang yang 'mengalami' Tuhan secara tahkik (muwahhid) dan yang berjalan (salik) di atas jalan dan thariqah Rasul menyala dan bersinar dari pohon yang diberkati, pohon zaitun yang tidak tumbuh di Timur dan tidak pula di Barat; yang minyaknya sudah hampir bisa menerangi tidak disentuh api; nurun 'ala nurin 'cahaya di atas cahaya'; Allah membimbing kepada cahaya-Nya orang-orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia [Madarij al-Salikin, juz III: 98].
Suluk, Realisasi Khalwat, 'Uzlah dan I'tikaf
Dalam tarekat sufi suluk dipahami dan diwujudkan dalam bentuk khalwat dan 'uzlah, yaitu mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu (10, 20, atau 40 hari) di sebuah tempat yang bebas dari kebisingan dan hiruk pikuk duniawi.
Teladan yang diambil oleh para salik dalam hal ini seperti ditegaskan Buya Hamka adalah kegemaran Nabi melakukan khalwat dan tahannuts di Gua Hira'. Imam al-Bukhari dan Muslim serta beberapa imam hadis lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa umm al-mu'min Aisyah berkata:
Nabi digemarkan oleh Allah untuk melakukan khalwat, beliau selalu berkhalwat di Gua Hira' dan melakukan tahannuts di sana, yaitu beribadah selama beberapa malam tertentu [Shahih al-Bukhari, juz I: 4; Shahih Muslim, juz I: 140; Shahih Ibn Hibban, juz I: 216; Musnad Ahmad, juz VI: 232].
Para sufi melakukan suluk di masjid-masjid atau surau-surau yang oleh al-Quran disebut sebagai rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk dimuliakan dan dijadikan tempat berdzikir menyebut asma-Nya [Al-Nur :36]. Rumah-rumah semacam inilah yang oleh para salik dijadikan tempat khalwat dan 'uzlah; mereka menetap disitu selama beberapa hari untuk melakukan ibadah dan dzikir secara intensif. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila suluk mereka disebut juga dengan I'tikaf yang dari segi bahasa bermakna berdiam di sebuah tempat selama jangka waktu tertentu.
Dalam kasus ini para salik merujuk kepada I'tikaf Nabi SAW selama sepuluh hari dalam bulan Ramadhan. Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa 'Aisyah ra. berkata:
Nabi SAW selalu I'tikaf selama sepuluh hari terakhir dari bulan bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau [Shahih al-Bukhari, juz II: 213; Shahih Muslim, juz II: 831].
Namun begitu, sebagaimana diceritakan oleh Abu Dzar al-Ghiffari, tidak jarang pula Nabi melakukan I'tikaf sepuluh hari pertama dan kadang-kadang sepuluh hari ke dua atau pertengahan dari bulan Ramadhan [Shahih al-Bukhari, juz II: 713; Shahih Muslim, juz II: 825].
Dan satu yang barangkali penting digarisbawahi di sini adalah bahwa I'tikaf pada dasarnya merupakan ibadah tersendiri; artinya tidak harus terkait dengan keharusan berpuasa dan tidak harus pula terkait dengan bulan Ramadhan. Imam al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn. Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:
Tidak ada keharusan berpuasa atas orang yang beri'tikaf kecuali ia menetapkan puasa itu untuk dirinya sendiri [Al-Mustadrak, juz I: 605; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, juz IV: 318; Sunan Daruquthi, juz II: 199]. Imam al-Baihaqi dan beberapa Imam hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa ia berkata:
Nabi SAW pernah melakukan I'tikaf selama sepuluh hari pertama bulan syawal [Sunan al-Baihaqi al-Kubra, juz IV: 318; Sunan Abi Dawud, juz II: 331; al-Sunan al-Kubra, juz II: 260].
Ibn al-Qayyim mengutip pendapat ulama yang mendukung keabsahan I'tikaf sebagai ibadah yang mandiri ketika ia mengatakan:
I'tikaf merupakan ibadah yang berdiri sendiri, sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya ibadah-ibadah lainnya seperti haji, salat, jihad dan ribath (merabit); I'tikaf adalah menetap di suatu tempat tertentu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya ribath (merabit); dan I'tifaf merupakan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) itu sendiri sehingga puasa tidak menjadi syarat dalam I'tikaf sebagaimana halnya haji [Hasyiyah Ibn al-Qayyim, juz VII: 106].
Satu hal yang pasti adalah bahwa suluk yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah SWT akan melahirkan manusia baru yang dari dalam hatinya memancar mata air dan sumber-sumber hikmah yang kemudian mengalir pada lisannya sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah:
Tidaklah seorang hamba mengikhlaskan dirinya selama empat puluh pagi (hari) kecuali dari kalbunya memancar sumber-sumber hikmah yang mengalir pada lisannya [Mushannaf Ibn Abi Syaibah, juz VII: 80; Musnad al-Syihab, juz I: 285].
Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa suluk dapat membidani kelahiran manusia baru yang utuh sehingga layak dijadikan sarana pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan yang selama ini lebih banyak menjadi slogan daripada kenyataan.
UNSUR THORIQOH III (SULUK)
Asas pertama tarekat adalah al-iradah, yaitu kehendak atau kemauan bulat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menapaki jalan-jalan (menujuNya) secara sungguh-sugguh sedemikan rupa sehingga yang bersangkutan benar-benar mengalami dan merasakan (kehadiran) Tuhan (Rukun Ihsan: Seolah-olah beribadah melihat Allah apabila tidak maka sadirilah bahwa Allah melihatnya). Perintah Tuhan mengenai hal ini sangat jelas ketika berfirman:
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah, serta bersungguh-sungguhlah menapaki jalan-jalan (menuju kepada)-Nya agar kamu memperoleh kemenangan/kesuksesan. (Al-Maidah :35).
Sebenarnya tidak hanya manusia yang diperintahkan Tuhan untuk menapaki jalan-jalan-Nya lebah-pun bahkan menjadi objek yang di-khitab Tuhan dengan perintah yang sama melalui wahyu yang disampaikan kepadanya, Maka tempuhlah jalan-jalan Tuhan -Mu yang telah dimudahkan untukmu [Al-Nahl : 69]. Dalam kasus lebah ini terdapat tanda ketuhanan yang layak direnungkan oleh murid (orang yang berkehendak bulat bertemu dengan Tuhan). Perjalanan menuju Tuhan tidak mungkin dapat dilakukan, dan jalan-jalan menuju Tuhan pun tidak akan pernah tersingkap, kecuali dengan mujahadah (perjuangan yang sungguh-sungguh) yang dimotori oleh iradah tersebut. Hal ini ditegaskan Tuhan dalam sebuah firman-Nya:
Dan orang-orang yang ber-mujahadah di dalam Kami, kepada mereka Kami benar-benar menunjukkan jalan-jalan menuju Kami; sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang yang mengalami ihsan (beribadah seolah-olah melihat Allah). (Al-Ankabut :69).
Dalam wacana sufi perjalanan dalam menempuh jalan-jalan menuju Tuhan disebut dengan suluk dan orang yang melakukan perjalanan disebut salik.
Di dalam suluk para salik menyibukan diri dengan riyadhah (latihan kejiwaan) dalam rangka pendekatan diri kepada Allah (al-taqarrub ilallah) melalui pengamalan ibadah-ibadah faraidh (wajib) dan nawafil (sunnah); semua aktivitas ini dilakukan diatas fondasi dzikrullah, di samping dzikrullah itu sendiri dijadikan sebagai amalan yang berdiri sendiri, lepas dari ibadah-ibadah lainnya, sebagai wujud konkret pengamalan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim:
Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya ketika ia berdzikir kepada-Ku; jika ia berdzikir kepada-Ku dalam dirinya,maka Aku berdzikir kepadanya dalam diri-Ku; jika ia berdzikir kepada-Ku dalam suatu kelompok, maka Aku berdzikir kepadanya dalam kelompok yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya sehasta; jika ia mendekat kepada-Ku sehasta; maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatanginya dalam keadaan berlari [Shahih al-Bukhari, juz VI: 2694; Shahih Muslim, juz IV: 2061].
Intinya semua sunnah Nabi sebagai model al-Quran yang hidup, nyata, dan sempurna, yang dalam bahasa Aisyah diungkapkan dengan redaksi akhlak Nabi adalah al-Quran [Musnad Ahmad, juz VI: 91; Al-Mu'jam al-Awsath, juz I: 30], diwujudkan secara konkret dan sungguh-sungguh dalam suluk. Berkekalan dalam wudhu, berdzikir dalam setiap keadaan (berdiri, duduk dan berbaring), berjamaah dalam semua salat wajib, menjaga moderasi antara lapar dan kenyang, menghiasi waktu malam dengan berbagai ibadah dan salat sunah, mengosongkan kalbu dari selain Allah, mengarahkan segenap konsentrasi dan perhatian sebagian contoh sunnah Nabi yang dipraktekkan dalam suluk.
Suluk sekaligus, merupakan jalan menuntut ilmu dan marifah yang dengannya Allah melempangkan jalan menuju sorga yang notabene jalan menuju Allah sendiri karena sorga tidak ada kecuali di sisi Allah. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan imam-imam hadis lainnya, mendukung kenyataan ini:
Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju sorga [Shahih al-Bukhari, juz I: 37; Shahih Muslim, juz IV: 2074; Musnad Ahmad, juz II: 325].
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah, serta bersungguh-sungguhlah menapaki jalan-jalan (menuju kepada)-Nya agar kamu memperoleh kemenangan/kesuksesan. (Al-Maidah :35).
Sebenarnya tidak hanya manusia yang diperintahkan Tuhan untuk menapaki jalan-jalan-Nya lebah-pun bahkan menjadi objek yang di-khitab Tuhan dengan perintah yang sama melalui wahyu yang disampaikan kepadanya, Maka tempuhlah jalan-jalan Tuhan -Mu yang telah dimudahkan untukmu [Al-Nahl : 69]. Dalam kasus lebah ini terdapat tanda ketuhanan yang layak direnungkan oleh murid (orang yang berkehendak bulat bertemu dengan Tuhan). Perjalanan menuju Tuhan tidak mungkin dapat dilakukan, dan jalan-jalan menuju Tuhan pun tidak akan pernah tersingkap, kecuali dengan mujahadah (perjuangan yang sungguh-sungguh) yang dimotori oleh iradah tersebut. Hal ini ditegaskan Tuhan dalam sebuah firman-Nya:
Dan orang-orang yang ber-mujahadah di dalam Kami, kepada mereka Kami benar-benar menunjukkan jalan-jalan menuju Kami; sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang yang mengalami ihsan (beribadah seolah-olah melihat Allah). (Al-Ankabut :69).
Dalam wacana sufi perjalanan dalam menempuh jalan-jalan menuju Tuhan disebut dengan suluk dan orang yang melakukan perjalanan disebut salik.
Di dalam suluk para salik menyibukan diri dengan riyadhah (latihan kejiwaan) dalam rangka pendekatan diri kepada Allah (al-taqarrub ilallah) melalui pengamalan ibadah-ibadah faraidh (wajib) dan nawafil (sunnah); semua aktivitas ini dilakukan diatas fondasi dzikrullah, di samping dzikrullah itu sendiri dijadikan sebagai amalan yang berdiri sendiri, lepas dari ibadah-ibadah lainnya, sebagai wujud konkret pengamalan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim:
Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya ketika ia berdzikir kepada-Ku; jika ia berdzikir kepada-Ku dalam dirinya,maka Aku berdzikir kepadanya dalam diri-Ku; jika ia berdzikir kepada-Ku dalam suatu kelompok, maka Aku berdzikir kepadanya dalam kelompok yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat kepadanya sehasta; jika ia mendekat kepada-Ku sehasta; maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatanginya dalam keadaan berlari [Shahih al-Bukhari, juz VI: 2694; Shahih Muslim, juz IV: 2061].
Intinya semua sunnah Nabi sebagai model al-Quran yang hidup, nyata, dan sempurna, yang dalam bahasa Aisyah diungkapkan dengan redaksi akhlak Nabi adalah al-Quran [Musnad Ahmad, juz VI: 91; Al-Mu'jam al-Awsath, juz I: 30], diwujudkan secara konkret dan sungguh-sungguh dalam suluk. Berkekalan dalam wudhu, berdzikir dalam setiap keadaan (berdiri, duduk dan berbaring), berjamaah dalam semua salat wajib, menjaga moderasi antara lapar dan kenyang, menghiasi waktu malam dengan berbagai ibadah dan salat sunah, mengosongkan kalbu dari selain Allah, mengarahkan segenap konsentrasi dan perhatian sebagian contoh sunnah Nabi yang dipraktekkan dalam suluk.
Suluk sekaligus, merupakan jalan menuntut ilmu dan marifah yang dengannya Allah melempangkan jalan menuju sorga yang notabene jalan menuju Allah sendiri karena sorga tidak ada kecuali di sisi Allah. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan imam-imam hadis lainnya, mendukung kenyataan ini:
Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju sorga [Shahih al-Bukhari, juz I: 37; Shahih Muslim, juz IV: 2074; Musnad Ahmad, juz II: 325].
ROBITHOH SEBAGAI PENGHALAU IBLIS
Melakukan rabithah pada dasarnya dimaksudkan sebagai realisasi atas perintah berjamaah yang dalam nash diungkapkan dengan berbagai redaksi. Imam al-Bukhari dalam al-Tarikh al-Kabir-nya mengutip sebuah hadis Nabi saw, Kalian harus berjamaah [al-Tarikh al-Kabir, juz VIII: 447], sementara Imam Ahmad dalam Musnad-nya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi saw. bersabda:
Wahai manusia, kalian harus berjamaah dan hindarilah bercerai-berai [Musnad Ahmad, juz V: 370].
Imam al-Tirmidzi dan al-Nasai meriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Umar berkhotbah menyampaikan sabda-sabda Nabi yang di dalamnya antara lain beliau bersabda:
Kalian harus berjamaah dan hindarilah bercerai (dari jamaah), karena setan bersama orang yang sendirian [Sunan al-Tirmidzi, juz IV: 465; al-Sunan al-Kubra, V: 388].
Dalam riwayat Imam al-Baihaqi hadis tersebut diungkapkan dengan redaksi:
Kalian harus berjamaah, karena tangan Allah ada di atas jamaah dan setan bersama orang yang sendirian [Syu’ab al-Iman, juz VII: 488]
Imam Abu al-Hujjaj al-Mazzi dalam Tahdzib al-Kamal mengutip ungkapan Ibn Mas’ud yang disampaikan oleh Amr ibn Maimun dengan redaksi:
Kalian harus berjamaah, karena sesungguhnya tangan Allah ada di atas jamaah dan Dia sangat menyukai jamaah [Tahdzib al-Kamal, juz XXII: 264].
Hadis-hadis di atas semuanya mengisyaratkan pentingnya berjamaah sebagai ajaran agama yang sangat fundamental, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Dalam shalat kita dianjurkan berjamaah; bahkan setengah ulama menghukumi shalat berjamaah itu wajib berdasarkan hadis-hadis Nabi yang antara lain mengancam akan membakar rumah-rumah penduduk yang dekat dengan mesjid tetapi penghuninya tidak mau shalat berjamaah [Shahih Muslim, juz I: 451; Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim, juz V: 153].
Tujuan paling pokok dari berjamaah adalah melindungi diri dari gangguan iblis yang selalu mencari celah untuk memalingkan manusia dari kebenaran menuju kesesatan, dan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan.
Kalau yang dimaksud berjamaah hanya semata-mata berjamaah secara jasmani, maka efektivitas perlindungan diri tidak akan tercapai secara maksimal, sebab yang menjadi sarang iblis adalah kalbu manusia, sehingga kalbu pun harus dikondisikan agar juga berjamaah, yaitu dengan melakukan rabithah (merabit mursyid).
Rabithah yang dilakukan secara berkesinambungan melahirkan berbagai fenomena positif sebagai karunia Tuhan yang jenisnya bergantung kepada kehendak-Nya, antara lain yang paling utama adalah mengalami atau merasakan kahadiran Tuhan. Apa yang dialami Nabi Yusuf as. ketika nyaris terjerumus dalam kemesuman merupakan salah satu indikasi atas kenyataan ini.
Di dalam al-Quran diceritakan bahwa Yusuf sudah nyaris melakukan perbuatan mesum bersama Zulaikha andaikata ia tidak melihat dan mengalami bukti Tuhannya. Ibn Abbas r.a. menjelaskan, yang dikutip oleh Imam al-Thabari dalam Tafsir-nya, bahwa ungkapan andaikata Yusuf tidak melihat bukti Tuhannya dalam surahYusuf ayat ke-24 tersebut adalah andaikata ia tidak melihat bayangan bentuk wajah ayahnya [Tafsir al-Thabari, juz XII: 186]. Dari penjelasan Ibn Abbas ini semakin jelas bahwa Yusuf mengalami rabithah secara otomatis dengan izin Allah.
Dalam hal berdzikir kepada Allah khususnya, melakukan rabithah merupakan keharusan, karena jalan yang ditempuh dalam berdzikir adalah jalan rohani yang sangat halus dan penuh dengan ranjau-ranjau iblis yang selalu berusaha memalingkannya dari jalan Allah untuk kemudian menjerumuskannya ke dalam kesesatan.
Dalam kaitan inilah Imam al-Nawawi al-Jawi menegaskan dalam kitabnya Nihayah al-Zayn, Orang yang berdzikir wajib mengikuti salah seorang Imam dari Imam-imam Tasawuf [Nihayah al-Zayn (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.) hal. 7]
Wahai manusia, kalian harus berjamaah dan hindarilah bercerai-berai [Musnad Ahmad, juz V: 370].
Imam al-Tirmidzi dan al-Nasai meriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Umar berkhotbah menyampaikan sabda-sabda Nabi yang di dalamnya antara lain beliau bersabda:
Kalian harus berjamaah dan hindarilah bercerai (dari jamaah), karena setan bersama orang yang sendirian [Sunan al-Tirmidzi, juz IV: 465; al-Sunan al-Kubra, V: 388].
Dalam riwayat Imam al-Baihaqi hadis tersebut diungkapkan dengan redaksi:
Kalian harus berjamaah, karena tangan Allah ada di atas jamaah dan setan bersama orang yang sendirian [Syu’ab al-Iman, juz VII: 488]
Imam Abu al-Hujjaj al-Mazzi dalam Tahdzib al-Kamal mengutip ungkapan Ibn Mas’ud yang disampaikan oleh Amr ibn Maimun dengan redaksi:
Kalian harus berjamaah, karena sesungguhnya tangan Allah ada di atas jamaah dan Dia sangat menyukai jamaah [Tahdzib al-Kamal, juz XXII: 264].
Hadis-hadis di atas semuanya mengisyaratkan pentingnya berjamaah sebagai ajaran agama yang sangat fundamental, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Dalam shalat kita dianjurkan berjamaah; bahkan setengah ulama menghukumi shalat berjamaah itu wajib berdasarkan hadis-hadis Nabi yang antara lain mengancam akan membakar rumah-rumah penduduk yang dekat dengan mesjid tetapi penghuninya tidak mau shalat berjamaah [Shahih Muslim, juz I: 451; Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim, juz V: 153].
Tujuan paling pokok dari berjamaah adalah melindungi diri dari gangguan iblis yang selalu mencari celah untuk memalingkan manusia dari kebenaran menuju kesesatan, dan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan.
Kalau yang dimaksud berjamaah hanya semata-mata berjamaah secara jasmani, maka efektivitas perlindungan diri tidak akan tercapai secara maksimal, sebab yang menjadi sarang iblis adalah kalbu manusia, sehingga kalbu pun harus dikondisikan agar juga berjamaah, yaitu dengan melakukan rabithah (merabit mursyid).
Rabithah yang dilakukan secara berkesinambungan melahirkan berbagai fenomena positif sebagai karunia Tuhan yang jenisnya bergantung kepada kehendak-Nya, antara lain yang paling utama adalah mengalami atau merasakan kahadiran Tuhan. Apa yang dialami Nabi Yusuf as. ketika nyaris terjerumus dalam kemesuman merupakan salah satu indikasi atas kenyataan ini.
Di dalam al-Quran diceritakan bahwa Yusuf sudah nyaris melakukan perbuatan mesum bersama Zulaikha andaikata ia tidak melihat dan mengalami bukti Tuhannya. Ibn Abbas r.a. menjelaskan, yang dikutip oleh Imam al-Thabari dalam Tafsir-nya, bahwa ungkapan andaikata Yusuf tidak melihat bukti Tuhannya dalam surahYusuf ayat ke-24 tersebut adalah andaikata ia tidak melihat bayangan bentuk wajah ayahnya [Tafsir al-Thabari, juz XII: 186]. Dari penjelasan Ibn Abbas ini semakin jelas bahwa Yusuf mengalami rabithah secara otomatis dengan izin Allah.
Dalam hal berdzikir kepada Allah khususnya, melakukan rabithah merupakan keharusan, karena jalan yang ditempuh dalam berdzikir adalah jalan rohani yang sangat halus dan penuh dengan ranjau-ranjau iblis yang selalu berusaha memalingkannya dari jalan Allah untuk kemudian menjerumuskannya ke dalam kesesatan.
Dalam kaitan inilah Imam al-Nawawi al-Jawi menegaskan dalam kitabnya Nihayah al-Zayn, Orang yang berdzikir wajib mengikuti salah seorang Imam dari Imam-imam Tasawuf [Nihayah al-Zayn (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.) hal. 7]
UNSUR THORIQOH II (ROBITHOH)
Dari segi bahasa makna rabithah adalah hubungan atau ikatan; terambil dari kata rabth yang berarti mengikat atau menghubungkan; [Al-Munawir Qamus ‘Arabi-Indunisi, hAL. 501]; Ungkapan rabithah al-mursyid, dengan demikian, menunjukan kepada makna menghubungkan diri dengan mursyid atau merabit dengan mursyid.
Di dalam al-Quran perintah melakukan rabithah diungkapkan melalui firman Tuhan:
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, serta merabitlah dan bertakwalah, agar kamu memperoleh kemenangan. (Ali Imran : 200).
Kata rabithu dalam ayat tersebut menurut Ibn Manzhur dalam Lisan al-Arab-nya bermakna hafizhu atau lazimu berkekalan/terus-menerus, yaitu al-muwazhabah ‘ala al-amr berkekalan/ terus-menerus melakukan sesuatu. Asal makna rabithu (ribath atau murabathah) adalah al-iqamah ‘ala jihad al-‘aduw (melakukan perang terhadap musuh) [Lisan al-Arab, juz VII: 303].
Pemahaman ideal mengenai maksud kata rabithu (ribath atau murabathah) dalam firman Allah tersebut, dengan menyimak makna-makna yang terkait dengan kata itu sendiri, muncul dalam thariqah, yaitu berkekalan/terus-menerus menghubungkan diri secara rohani dengan mursyid dalam rangka memerangi iblis sebagai musuh manusia yang paling nyata. Tidak ada musuh yang paling layak untuk selalu diwaspadai dan diperangi kecuali iblis la’natullah yang memang berusaha terus menghancurkan manusia.
Lebih jauh dapat dikatakan bahwa rabithah al-mursyid (merabit mursyid) pada dasarnya adalah berjamaah secara rohani dengan mursyid, yaitu imam-berimam dalam khafilah rohani Rasulullah SAW. Menunjuk kepada pengertian inilah Imam Ja’far al-Shadiq, tokoh sufi dari kalangan ahli bait Nabi SAW, yang dikutip oleh Abu Nu’aim al-Ishfahani dalam ensiklopedia orang-orang suci–nya yang berjudul Hilyat al-Awliya mengatakan:
Barangsiapa menjalani hidup dengan bergabung dalam batin (rohani) Rasul, maka dialah yang disebut orang sufi [Hilyat al-Awliya’, juz I hal. 20].
Di samping itu, dapat pula dikatakan bahwa rabithah al-mursyid (merabit mursyid) menunjuk kepada makna melibatkan Rasul SAW dalam setiap munajat dan ibadah agar munajat dan ibadah itu dapat langsung mendapat sambutan dari Allah sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah:
Andaikata mereka ketika menzalimi diri mereka datang kepadamu (Muhammad), kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati bahwa Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. (Al-Nisa’ : 64).
Melibatkan Rasul SAW atau merabit mursyid dalam ibadah dapat disimak pula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis lainnya disebutkan bahwa ketika Umar meminta izin kepada Nabi saw untuk menunaikan ibadah umrah, Nabi SAW bersabda:
"Wahai saudara mudaku, serikatkan (libatkan) kami dalam doamu dan jangan lupakan kami [Sunan al-Tirmidzi, juz V: 559; Musnad Ahmad, juz II: 59; Sunan Ibn Majah, juz II: 966].
Dalam kasus yang berbeda, melibatkan Rasul SAW atau merabit mursyid dapat disimak dari kisah Umar ibn al-Khaththab r.a. yang melibatkan Paman Nabi SAW yang bernama Abbas ra. ketika ia berdoa memohon hujan:
"Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada-Mu dengan nabi-Mu, lalu engkau memberi kami hujan. Sekarang, kami bertawassul kepada-Mu dengan paman nabi-Mu, maka berilah kami hujan. Mereka pun kata sang perawi hadis diberi hujan oleh Allah [Shahih al-Bukhari, juz I: 342, juz III: 1360; Shahih Ibn Hibban, juz VII: 110- 111 dan Sunan al-Baihaqii al-Kubra, juz III: 352, al-Mu’jam al-Kabir, juz I: 72].
Artinya, Umar melibatkan ‘Abbas ra. sebagai pengganti Rasul SAW untuk mendapatkan karunia Allah SWT berupa hujan. Dengan melibatkan ‘Abbas ra. sesungguhnya Umar ra . hendak bergabung dalam khafilah rohani Rasul SAW melalui orang yang masih hidup dan yang dicintai Rasul SAW meskipun Umar ra. sendiri memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasul SAW.
Berdasarkan hal ini, maka orang-orang mukmin lainnya, apalagi yang hidup pada masa sekarang, sudah seyogianya mencari seorang hamba Allah SWT yang karena kecintaan dan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW layak dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW dan layak pula menduduki posisi sebagai khalifah pengganti Rasul SAW.
Di dalam al-Quran perintah melakukan rabithah diungkapkan melalui firman Tuhan:
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, serta merabitlah dan bertakwalah, agar kamu memperoleh kemenangan. (Ali Imran : 200).
Kata rabithu dalam ayat tersebut menurut Ibn Manzhur dalam Lisan al-Arab-nya bermakna hafizhu atau lazimu berkekalan/terus-menerus, yaitu al-muwazhabah ‘ala al-amr berkekalan/ terus-menerus melakukan sesuatu. Asal makna rabithu (ribath atau murabathah) adalah al-iqamah ‘ala jihad al-‘aduw (melakukan perang terhadap musuh) [Lisan al-Arab, juz VII: 303].
Pemahaman ideal mengenai maksud kata rabithu (ribath atau murabathah) dalam firman Allah tersebut, dengan menyimak makna-makna yang terkait dengan kata itu sendiri, muncul dalam thariqah, yaitu berkekalan/terus-menerus menghubungkan diri secara rohani dengan mursyid dalam rangka memerangi iblis sebagai musuh manusia yang paling nyata. Tidak ada musuh yang paling layak untuk selalu diwaspadai dan diperangi kecuali iblis la’natullah yang memang berusaha terus menghancurkan manusia.
Lebih jauh dapat dikatakan bahwa rabithah al-mursyid (merabit mursyid) pada dasarnya adalah berjamaah secara rohani dengan mursyid, yaitu imam-berimam dalam khafilah rohani Rasulullah SAW. Menunjuk kepada pengertian inilah Imam Ja’far al-Shadiq, tokoh sufi dari kalangan ahli bait Nabi SAW, yang dikutip oleh Abu Nu’aim al-Ishfahani dalam ensiklopedia orang-orang suci–nya yang berjudul Hilyat al-Awliya mengatakan:
Barangsiapa menjalani hidup dengan bergabung dalam batin (rohani) Rasul, maka dialah yang disebut orang sufi [Hilyat al-Awliya’, juz I hal. 20].
Di samping itu, dapat pula dikatakan bahwa rabithah al-mursyid (merabit mursyid) menunjuk kepada makna melibatkan Rasul SAW dalam setiap munajat dan ibadah agar munajat dan ibadah itu dapat langsung mendapat sambutan dari Allah sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah:
Andaikata mereka ketika menzalimi diri mereka datang kepadamu (Muhammad), kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati bahwa Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. (Al-Nisa’ : 64).
Melibatkan Rasul SAW atau merabit mursyid dalam ibadah dapat disimak pula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis lainnya disebutkan bahwa ketika Umar meminta izin kepada Nabi saw untuk menunaikan ibadah umrah, Nabi SAW bersabda:
"Wahai saudara mudaku, serikatkan (libatkan) kami dalam doamu dan jangan lupakan kami [Sunan al-Tirmidzi, juz V: 559; Musnad Ahmad, juz II: 59; Sunan Ibn Majah, juz II: 966].
Dalam kasus yang berbeda, melibatkan Rasul SAW atau merabit mursyid dapat disimak dari kisah Umar ibn al-Khaththab r.a. yang melibatkan Paman Nabi SAW yang bernama Abbas ra. ketika ia berdoa memohon hujan:
"Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada-Mu dengan nabi-Mu, lalu engkau memberi kami hujan. Sekarang, kami bertawassul kepada-Mu dengan paman nabi-Mu, maka berilah kami hujan. Mereka pun kata sang perawi hadis diberi hujan oleh Allah [Shahih al-Bukhari, juz I: 342, juz III: 1360; Shahih Ibn Hibban, juz VII: 110- 111 dan Sunan al-Baihaqii al-Kubra, juz III: 352, al-Mu’jam al-Kabir, juz I: 72].
Artinya, Umar melibatkan ‘Abbas ra. sebagai pengganti Rasul SAW untuk mendapatkan karunia Allah SWT berupa hujan. Dengan melibatkan ‘Abbas ra. sesungguhnya Umar ra . hendak bergabung dalam khafilah rohani Rasul SAW melalui orang yang masih hidup dan yang dicintai Rasul SAW meskipun Umar ra. sendiri memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasul SAW.
Berdasarkan hal ini, maka orang-orang mukmin lainnya, apalagi yang hidup pada masa sekarang, sudah seyogianya mencari seorang hamba Allah SWT yang karena kecintaan dan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW layak dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW dan layak pula menduduki posisi sebagai khalifah pengganti Rasul SAW.
UNSUR THORIQOH I (MURSYID)
Mursyid
Kata mursyid berasal dari bahasa Arab dan merupakan ism fa’il (Ingg. Present participle) kata kerja arsyada – yursyidu yang berarti “membimbing, menunjuki (jalan yang lurus)”, terambil dari kata rasyad ‘hal memperoleh petunjuk/kebenaran’ atau rusyd dan rasyada ‘hal mengikuti jalan yang benar/lurus’ [Lisan al-Arab, juz III: 175-176].
Dengan demikian, makna mursyid adalah “(orang) yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus” Dalam wacana tasawuf/tarekat mursyid sering digunakan dengan kata Arab Syaikh; kedua-duanya dapat diterjemahkan dengan “guru”.
Dalam al-Quran kata mursyid muncul dalam konteks hidayah (petunjuk) yang dioposisikan dengan dhalalah (kesesatan), dan ditampilkan untuk menyipati seorang wali yang oleh Tuhan dijadikan sebagai khalifah-Nya untuk memberikan petunjuk kepada manusia:
‘Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia benar-benar mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, maka orang itu tidak akan pernah engkau dapati memiliki wali mursyid (pemimpin yang mampu memberi petunjuk).” (Al-Kahfi :17)
Kata wali (jamak: awliya) sendiri menunjukan kepada beberapa makna, antara lain al-nashir ‘penolong’ [Lisan al-Arab, XV: 406], al-mawla fi al-din ‘pemimpin spiritual’[Lisan al-Arab juz XV: 408], al-shadiq ‘teman karib’ dan al-tabi al-muhibb ‘pengikut yang mencintai’ [Lisan al-Arab, juz XV:411] Semua makna ini berserikat dan secara simultan menjelaskan makna wali dalam ayat diatas, yaitu “orang yang mencintai dan dicintai Allah sehingga layak menjadi pemimipin spritual yang harus diikuti”.
Pengertian wali semacam ini digambarkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan beberapa imam hadis lainnya dengan redaksi:
“Barangsiapa memusuhi seorang wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai berupa ibadah-ibadah yang Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku itu terus menerus mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah, kecuali Aku pasti dengannya ia mendengar, (Akulah) matanya yang dengannya ia melihat, (Akulah) tangannya yang dengannya ia melakukan sesuatu, dan (Akulah) kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku niscaya Aku mengabulkannya; dan jika ia memohon perlindungan kepada-Ku niscaya Aku melindunginya [Shahih al-Bukhari, V: 2384; Shahih Ibn Hibban, II: 58; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, juz III: 346].
Menurut berbagai riwayat yang sahih, wali-wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang memiliki karakteristik utama “tidak pernah lepas dari berdzikir kepada Allah” sebagaimana halnya Nabi saw yang oleh ‘Aisyah dengan “selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap detik yang beliau milik” (kana yadzkurullaha fi kulli ahyanihi) [Musnad Abi Ya’la, juz VIII: 355]. Imam al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir-nya meriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Sesungguhnya di antara manusia ada kunci-kunci dzikrullah; apabila mereka dilihat orang maka (yang melihat) itu langsung berdzikir kepada Allah” [Al-Mu’jam al-Kabir, juz X:205].
Maksud “kunci-kunci dzikrullah” dalam riwayat tersebut adalah wali-wali Allah sesuai dengan hadis dalam riwayat Ibn Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah saw ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah wali-wali Allah itu? Beliau menjawab:
“Orang-orang yang apabila mereka dilihat orang maka orang (yang melihat) itu berdzikir kepada Allah karena melihat mereka” [ Mushaannaf Ibn Abi Syaibah, juz VII: 79; Musnad al-Bazza,juz VII: 158].
Imam al-Tirmidzi juga meriwayatkan:
"Nabi Musa as pernah bertanya kepada Tuhannya, “Tuhan, siapakah wali-wali-Mu?” Tuhan menjawab:“Orang-orang yang apabila mereka berdzikir engkau pun berdzikir dan apabila engkau berdzikir mereka pun berdzikir” Nawadir al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, juz IV: 86].
Imam al-Suyuthi mengutip sebuah riwayat yang menceritakan bahwa kaum Hawariyyun bertanya kepada Nabi Isa as, “Siapa wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih?” Nabi Isa menjawab:“Orang-orang yang memandang hakikat dunia sementara manusia memandang permukaannya, dan orang-orang yang memandang dunia yang abadi (akhirat) sementara manusia memandang dunia yang fana” [Tafsir al-Durr al-Mantsur, juz IV: 370].
Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang yang bukan nabi dan bukan pula syuhada’ tetapi pada hari kiamat para Nabi dan syuhada’ menginginkan seperti mereka karena kedudukan mereka disisi Allah ‘azza wa jalla.”
Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa mereka dan apa amal-amal mereka? Boleh jadi kami akan mencintai mereka.” Rasulullah bersabda , “Mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan ruh Allah tidak atas dasar hubungan darah antara mereka dan tidak pula atas dasar harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, wajah mereka adalah nur (Allah) dan mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur; mereka tidak takut ketika orang lain takut”. Kemudian Rasulullah membacakan ayat “Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih (Q.S. Yunus,:62).” Hadis tersebut dikutip oleh Imam al-Jauzi dari jalur ‘Umar Ibn al-Khaththab r.a. dalam Zad al-Masir-nya, [Zad al-Masir, juz IV: 43-44], dan dikutip juga oleh Imam Ibn Hibban dalam Shahih-nya [Shahih Ibn Hibbam juz II: 332], dan oleh Imam al-Bayhaqi dalam al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab [al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab, juz I:134], dari jalur Abu Hurairah.
Mursyid sebagai Pemandu Jalan
Mursyid dalam thariqah adalah seorang wali yang layak diikuti sebagai imam dalam perjalanan menuju Tuhan. Ia adalah wali Allah yang ciri khasnya sebagaimana disebutkan di atas. Jalan menuju Tuhan bukan jalan yang mulus melainkan jalan yang berliku-liku dan penuh dengan rintangan-rintangan berupa ranjau-ranjau Iblis sehingga diperlukan pemandu yang arif untuk bisa selamat dari semua rintangan itu. Seorang salik, orang yang menempuh perjalanan (menuju Tuhan) atau yang biasa disebut dengan murid, yang telah membulatkan kehendaknya untuk menempuh perjalanan (menuju Tuhan) tidak boleh tidak harus didampingi mursyid sebagai pemandu jalan yang menuntun dan sekaligus memperingatkannya apabila ada bahaya yang mengancam. Keberadaan seorang mursyid dengan fungsi ini sangat mutlak.
Barang siapa berjalan tanpa pemandu, ia memerlukan dua ratus tahun untuk perjalanan dua hari, kata Jalaluddin Rumi dalam Matsnawi yang dikutip oleh Annemarie Schimmel [Dimensi Mistik dalam Islam, hal. 106], untuk menggambarkan betapa sulitnya perjalanan itu dan betapa pentingnya keberadaan seorang pemandu (mursyid).
Posisi mursyid atau syaikh sufi menurut Ibn Taimiyah tidak ubahnya seperti imam dalam shalat dan pemandu haji (dalil-al-hajj); imam shalat diikuti oleh makmum, mereka shalat sesuai dengan shalatnya imam (yushalluna bi shalatihi), sedangkan pemandu haji menunjukan kepada jamaah jalan menuju baitullah (yadullu al-wafd ala thariq al-bait)[ Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, VIII: 49].
Dalam peristiwa Isra dan Miraj (perjalanan Nabi menuju Tuhan), Nabi saw dipandu oleh Jibril as yang berfungsi sebagai mursyid, imam atau guide, yaitu pemandu jalan yang menuntun dan membimbing beliau hingga sampai di hadirat Allah ‘azza wa jalla.
Dalam Tafsir al-Thabari disebutkan bahwa dalam Miraj itu, Nabi saw bertemu dengan seorang tua renta di sisi jalan, dan ketika beliau bertanya siapa orang itu, Jibril as. berkata, Teruslah berjalan, wahai Muhammad (sir ya muhammad)!
Beliau juga mendengar sebuah suara yang menyeru beliau agar menyingkir dari jalan, “Halumma ya muhammad, ke sinilah Muhammad!, sebelum Nabi saw sempat menoleh Jibril sudah langsung memperingatkan, Teruslah berjalan, wahai muhammad (sir ya muhammad)!
Beberapa saat kemudian Jibril memberikan penjelasan. Orang tua yang engkau lihat di sisi jalan tadi menunjukan bahwa tidak tersisa dari dunia ini kecuali sekadar sisi umur orang tua itu, sedangkan suara yang hendak memalingkanmu adalah Iblis [Tafsir al-Thabari, juz XV: 6; Tafsir Ibn Katsir, juz III: 6 Al-Ahadits al-Mukhtarah, juz VI: 258].
Peristiwa Isra dan Miraj Nabi saw memang menjadi rujukan utama para sufi, terutama yang berkenaan dengan unsur Jibril as. yang berfungsi sebagai mursyid, sang pemandu.
Keberadaan unsur Jibril as sangat mutlak sedemikian rupa sehingga andaikata unsur ini tidak ada, maka Nabi saw akan terperangkap oleh jebakan Iblis. Lalu bagaimana dengan umat beliau? Apakah mereka juga memerlukan unsur Jibril ini? Jawabannya pasti: ya, tidak boleh tidak. Posisi dan fungsi unsur Jibril ini justru diduduki dan dilaksanakan oleh Nabi sendiri.
Urgensi unsur Jibril sangat jelas terutama mengingat pernyataan Nabi saw bahwa shalat adalah miraj-nya orang mukmin [Syarh Sunan Ibn Majah, hal. 313]. Artinya, orang-orang mukmin juga dimungkinkan mengalami miraj dengan izin dan kehendak Tuhan. Sebagai sarana miraj, dalam shalat seorang mukmin harus melibatkan unsur Jibril; kalau tidak, maka shalatnya akan didominasi oleh unsur setan, sehingga shalat itu menjadi shalat yang tanpa makna, gersang, dan jauh dari nilai-nilai khusyuk, yang pada gilirannya tidak dapat berfungsi sebagai tanha an al-fahsya wa al-munkar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar [al-Ankabut :45].
Shalat semacam ini kata Nabi saw dalam riwayat al-Thabrani dengan perawi-perawi sahih [Majma al-Zawaid, juz II: 258], adalah shalat yang hanya akan menjauhkan pelakunya dari Allah SWT (man lam tanhahu shalatuhu an al-fahsya wa al-munkar lam yazdad minallahi illa budan), [Al-Mu’jam al-Kabir, juz XI: 54]. Berbagai kasus dalam kehidupan orang-orang mukmin menjadi bukti tak terbantah atas pernyataan ini.
Miraj adalah karunia Tuhan yang berupa perjalanan menuju Dia SWT dengan perbentangan berbagai fenomena ghaib (metafisik) sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.
Dalam sejarah Nabi saw dikenal dua jenis miraj: Khusus dan umum.
Miraj khusus dialami Nabi saw pada saat beliau menerima perintah shalat wajib lima waktu, sedangkan miraj umum dialami Nabi saw pada saat-saat yang lain termasuk ketika beliau dimuliakan Allah dengan diangkat sebagai rasul.
Dalam wacana sufi miraj umum lebih sering disebut dengan istilah muraqabah, dan sangat dimungkinkan dialami oleh siapa pun dari kalangan orang-orang beriman. Pengalaman melihat sorga dan neraka dengan mata kepala (muraqabah) yang dialami para sahabat merupakan indikasi nyata atas kemungkinan ini.
Dalam kitab Shahih-nya Imam Muslim memuat bab yang menyinggung soal muraqabah; di dalamnya diriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Hanzhalah al-Usayyidi, salah seorang sekretaris Rasulullah saw; ia berkata bahwa ketika Nabi bercerita tentang sorga dan neraka, ia dan Abu Bakar ra. merasa melihat sorga dan neraka itu dengan mata kepala mereka, tetapi masing-masing dari mereka banyak yang lupa apa yang mereka lihat, lalu mereka memutuskan untuk menghadap Nabi saw dan menanyakan hal itu. Dialog antara Hanzhalah dan Nabi dapat disimak dari kutipan berikut:
Aku (Hanzhalah) berkata, Hanzhalah telah munafik, wahai Rasulullah. Rasulullah saw bertanya, Ada apa?. Aku (Hanzhalah) berkata, Wahai Rasulullah, kami pernah berada di hadapanmu mendengarkan engkau bercerita kepada kami tentang sorga dan neraka sehingga kami seolah-olah melihat sorga dan neraka itu dengan mata kepala. Setelah kami pulang dari hadapanmu, serta bertemu dan bermain-main dengan anak-istri kami dan pergi keperkarangan kami, kami banyak lupa tentang hal itu. Rasulullah saw bersabda, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kalian berkekalan dengan apa yang kalian lihat dihadapanku dan berkekalan dalam dzikir, niscaya para malaikat menjabat tangan kalian diatas tempat tidur kalian dan dijalan-jalan (tarekat-tarekat) kalian. Sayangnya, wahai Hanzhalah, (muraqabah itu) hanya sesaat dan sesaat (ini diucapkan tiga kali oleh beliau)” [Shahih Muslim, juz IV: 2106; Musnad Ahmad, juz IV: 346; Sunan al-Tirmidzi, juz IV: 666].
Dalam kasus tersebut para sahabat telah mengalami muraqabah dan sekaligus miraj, karena miraj pada dasarnya dapat dipahami sebagai naik dan melintasi alam fisik, keluar dari dimensi ruang dan waktu, serta memasuki dan menyaksikan alam metafisik ketuhanan. Pengalaman miraj para sahabat tersebut terjadi berkat bimbingan Rasul saw sebagai pemandu, sebagaimana Rasul sendiri mengalami miraj berkat bimbingan Jibril as. dengan izin Allah SWT. Dengan kata lain, mereka dibawa miraj oleh Nabi saw sebagaimana Nabi dibawa miraj oleh Jibril as. dengan izin Allah. (Lalu, bagaimana dengan orang-orang mukmin lain yang tidak bertemu dengan Nabi? Siapa yang akan membawa mereka miraj?!).
Hikmah yang dapat diambil dari pengalaman itu adalah bahwa yang bersangkutan pasti menyadari secara haqqul yaqin bahwa ungkapan al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun (kami milik Allah dan kepada-Nya kami pulang) [Al-Baqarah :156] adalah benar (haqq), dan bahwa mereka ketika hidup di dunia pada hakikatnya sedang berada dalam perjalanan pulang menuju Tuhan, sebuah perjalanan yang sangat sulit dan berliku-liku.
Dengan adanya seorang pemandu, perjalanan itu akan terasa lebih ringan, mudah, dan lancar sehingga tepat sekali ungkapan Rumi yang dikutip sebelumnya, Barangsiapa berjalan tanpa pemandu, ia memerlukan dua ratus tahun untuk perjalanan dua hari.
Mursyid sebagai Khalifah Rasul
Imam-imam hadis, selain al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan sebuah hadis perpisahan yang didalamnya antara lain Nabi saw bersabda:
Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa al-rasyidun yang memperoleh petunjuk; berpeganglah kepada sunnah-sunnah itu dan ‘gigitlah’ sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian [Shahih Ibn Hibban, juzI: 179; sunan al-Tirmidzi, juz V: 44; Sunan Abi Dawud, juz IV: 200; Sunan Ibn Majah, juz I: 16; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, juz X:114].
Dalam hadis itu tampak bahwa sunnah Nabi saw disandingkan dengan sunnah para khalifah (pengganti) beliau; kedua jenis sunnah ini sama-sama wajib diikuti dan dipegangi secara teguh oleh setiap mukmin. Ini menunjukan bahwa sunnah al-khulafa al-rasyidun adalah sunnah yang suci sebagaimana Sunnah Nabi saw sendiri. Tidak mungkin Nabi saw memerintahkan mengikuti sunnah mereka apabila sunnah itu mengandung cacat atau hal-hal yang bertentangan dengan syara.
Siapakah sesungguhnya yang dimaksud dengan al-khulaf al-rasyidun itu? Selama ini ungkapan al-khulafa al-rasyidun dipahami sebagai pengganti Nabi saw di bidang politik, yaitu sebagai kepala negara/pemerintahan Islam yang bertanggung jawab atas semua urusan politik umat. Mereka adalah Abu Bakar al-Shiddiq ra., Umar Ibn al-Khaththab ra., Utsman Ibn Affan ra., dan Ali Ibn Abi Thalib ra.
Belakangan nama Amirul Mukminin Umar Ibn Abd al-Aziz ra diposisikan sebagai khalifah kelima dan sekaligus terakhir dari al-khulafa al-rasyidun, sehingga secara keseluruhannya al-khulafa al-rasyidun dalam pengertian ini hanya berjumlah lima orang. Tetapi di samping pengertian sebagai pengganti Nabi saw di bidang politik, pengertian al-khulafa al-rasyidun juga dapat ditinjau dari segi spiritual, sebab Nabi saw tidak sekedar sebagai kepala negara/pemerintahan melainkan juga sebagai Nabi dan Rasul yang membawa misi tauhid dan ubudiah serta penyempurnaan akhlak yang mulia.
Beliau adalah pemimpin spiritual yang oleh al-Quran digambarkan memiliki tugas-tugas:
(1) membacakan kepada umat ayat-ayat Tuhan, (2) menyucikan kalbu mereka, serta (3) mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah [Ali Imran : 164].
Tugas-tugas seorang khalifah sudah sepatutnya sesuai dengan tugas-tugas Nabi saw sebagai seorang Rasul, yaitu ta’lim (mengerjakan al-Kitab dan al-Hikmah) dalam kerangka tauhid, ubudiah, dan penyempurnaan akhlak yang mulia. Dengan pengertian kedua ini, al-khulafa al-rasyidun pada dasarnya menunjuk kepada ulama yang oleh Nabi SAW. diposisikan sebagai waratsah al-anbiya (ahli waris para Nabi), dan satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa Nabi saw atau Nabi-Nabi lainnya tidak mewariskan dinar atau dirham; mereka hanya mewariskan al-ilm (ilmu) [Musnad Ahmad, V: 196; Shahih al-Bukhari, I: 46]. Mereka itulah hamba-hamba pilihan yang kepada mereka Allah mewariskan al-Quran [Fathir, 35:32], sehingga mereka disebut dengan ahl al-dzikr yang kepada mereka setiap orang harus bertanya [Al-Nahl, :43; al-Anbiya, :7].
Ciri khas mereka adalah bahwa mereka tidak pernah meminta upah atas upaya dakwah mereka karena Nabi saw juga tidak meminta upah atas dakwah beliau [Yusuf : 104]; dan Allah memerintahkan agar mengikuti orang-orang yang tidak pernah meminta upah seperti mereka [Yasin :21, Al Furqan :57].
Dengan warisan ciri khas semacam ini mereka layak menyandang gelar khalifah (pengganti) Rasul yang sekaligus sebagai penegak hujjah Allah, dan jumlah mereka tentu tidak hanya lima orang meskipun juga tidak banyak.
Sebagai hamba-hamba pilihan Tuhan, jumlah mereka memang sedikit sebagaimana ditegaskan oleh sayyidina Ali Ibn Thalib r.a. ketika berkata kepada Kuhail ibn-Ziyad, Demi Allah, sungguh bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang menegakkan hujjah-hujjah Allah agar tanda-tanda kebesaran-Nya tidak hilang dan hujjah-Nya tidak terbantahkan. Mereka adalah orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit, namun sangat agung dan terhormat di sisi Allah.
Bahwa al-khulafa al-rasyidun yang dimaksud oleh Nabi saw lebih terkait dengan khalifah-khalifah spiritual daripada khalifah-khalifah di bidang politik dapat disimak pula dari kenyataan bahwa Umar Ibn al-Khaththab ra dan beberapa sahabat lainnya ternyata masih diperintahkan oleh Nabi saw agar menemui dan meminta syafaat kepada Uwais al-Qarni ra, seorang laki-laki dalam hadis riwayat Imam Muslim disebut sebagai khayr al-tabiin, orang terbaik di antara orang-orang yang hidup pada masa sahabat;
Sesungguhnya tabiin terbaik adalah seseorang yang bernama Uwais; dia hanya punya seorang ibu dan juga punya penyakit kusta; maka mintalah kepadanya agar ia memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian [Shahih Muslim, juz IV: 1968; Musnad Ahmad, juz I: 38].
Berkaitan dengan diri Uwais al-Qarni ra inilah, dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah r.a., disebutkan bahwa Nabi saw bersabda:
Iman ada di Yaman dan hikmah pun ada di Yaman (dalam riwayat lain ada tambahan: dan aku cium nafas al-rahman dari arah Yaman, atau, dan aku cium nafas Tuhanmu dari arah Yaman) [ Shahih al-Bukhari, III: 1289; Shahih Muslim, I: 72 dan Shahih Ibn Hibban, XVI: 288].
Nafas al-rahman yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah Uwais al-Qarni. Dia adalah wali Allah yang paling besar pada masanya; disembunyikan oleh Allah di tengah-tengah rakyat jelata sehingga orang-orang tidak mengetahuinya dan bahkan sering mengejeknya. Dia berasal dariku dan aku berasal darinya, kata Rasulullah saw [Al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab,juz I:113].
Ungkapan Rasul ini menunjukan kepada hubungan spiritual antara Uwais al-Qarni ra dan Nabi saw meskipun ia belum pernah bertemu dengan beliau.
Kualifikasi Mursyid
Dengan menyimak misi, tugas-tugas, dan ciri khas dakwah Rasulullah saw dan para khalifah (pengganti) beliau dapat dipahami bahwa tidak setiap ulama dapat serta-merta menjadi Mursyid terutama dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dan guru spiritual, karena diantara ulama ada pula bahkan banyak sekali yang sekedar berbaju ulama tetapi prilakunya justru bertentangan dengan esensi ulama itu sendiri, yaitu takut kepada Allah sebagaimana diisyaratkan al-Quran:
Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama (Fathir :28).
Di antara mereka banyak pula yang terbuai oleh harta dan kenikmatan duniawi; mereka tidak berdakwa kecuali upah yang akan diperolehnya sudah jelas. Ulama semacam ini oleh Imam al-Ghazali disebut dengan ulama dunia atau ulama su’ (jahat) :
Diantara perkara-perkara yang paling penting adalah mengetahui tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Yang dimaksud dengan ulama dunia disini adalah ulama su’ yang bertujuan mengejar kenikmatan dunia serta memburu kehormatan dan kedudukan di antara ahli ilmu [Ihya Ulum al-Din, juz I: 58].
Oleh karena itu ketika berbicara tentang kualifikasi seorang Mursyid, Imam al-Ghazali menjadikan kebebasan dari kecintaan terhadap harta dan kedudukan sebagai kriteria awal:
Mursyid adalah orang yang:
(1) dari batinnya sudah keluar kecintaan terhadap harta dan kedudukan;
(2) format pendidikannya berlangsung di tangan seorang Mursyid juga, dan begitulah seterusnya hingga silsilah itu berakhir pada Nabi saw;
(3) mengalami riyadhah (latihan jiwa) seperti sedikit makan, bicara, dan tidur, serta banyak melakukan salat, sedekah dan puasa;
(4) memperoleh cahaya dari cahaya-cahaya Nabi saw;
(5) terkenal kebaikan biografinya dan kemulian akhlaknya seperti sabar, syukur, tawakal, yakin, damai, dermawan, qanaah, amanah, lemah lembut, rendah hati, berilmu, jujur, berwibawa, malu, tenang, tidak tergesa-gesa, dan lain sebagainya;
(6) suci dari akhlaq yang tercela seperti sombong, kikir, dengki, tamak, berangan-angan panjang, gegabah dan lain sebagainya;
(7) bebas dari ekstremitas orang-orang yang ekstrem; dan
(8) kaya dengan ilmu yang diperoleh langsung dari Rasulullah saw sehingga tidak membutuhkan ilmu orang-orang yang mengada-ada (ilm al-mukallafin) [Khulashah al-Tashanif al-Tashawwuf dalam Majmu Rasail al-Imam al-Ghazali, hal. 173].
Sedikit berbeda dari Imam al-Ghazali, al-Mukarram Saidi Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengumumkan kualifikasi sebagai berikut:
1. Pilih Guru yang Mursyid, dicerdikan oleh Allah SWT, bukan dicerdikan oleh yang lain-lain, dengan izin dan ridha Allah, karena Allah.
2. Yang kamil mukamil (sempurna dan menyempurna), diberi karunia oleh Allah, karena Allah.
3. Yang memberi bekas pengajarannya, (kalau ia mengajar atau mendoa berbekas pada si murid, si murid berobah kearah kebaikan), berbekas pengajarannya itu, dengan izin dan ridha Allah, biidznillah.
4. Yang masyhur kesana kemari, kawan dan lawan mengatakan, ia seorang Guru Besar.
5. Yang tidak dapat dicela oleh orang yang berakal akan pengajarannya, yaitu tidak dapat dicela oleh hadits dan Qur’an dan oleh ilmu pengetahuan (tidak bersalah-salahan dengan hadits, Qur’an dan akal).
6. Tidak setengah kasih kepada dunia, karena bulatnya hatinya, kasih kepada Allah. Ia ada giat bergelora dalam dunia, bekerja hebat dalam dunia, tetapi bukan karena kasih kepada dunia itu, tetapi karena prestasinya itu adalah sebagai abdinya kepada Allah SWT dalam hidupnya.
7. Mengambil ilmu dari orang yang tertentu; Gurunya harus mempunyai tali yang nyata kepada Allah dan Rasul dengan silsilah yang nyata [Ibarat Sekuntum Bunga dari Taman Firdaus, hal. 173].
Wasilah (Nurun ‘ala Nurin)
Ungensi posisi Mursyid yang sangat penting dalam thariqah sebagai jalan menuju Tuhan sebenarnya erat kaitannya dengan masalah wasilah yang oleh Allah diperintahkan agar orang-orang mukmin mencarinya:
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (yang menyampaikanmu) kepada Allah, serta berjuanglah di jalan-Nya, agar kamu menang. (al-Maidah :35)
Dari uraian-uraian berikut akan dipahami bahwa Mursyid adalah pembawa wasilah sebagaimana Jibril adalah pembawa Buraq yang oleh Imam Zubaidi disebut sebagai kendaraan para nabi [Syarh al-Nawawi Shahih Muslim, juz II: 210]
Kata mursyid berasal dari bahasa Arab dan merupakan ism fa’il (Ingg. Present participle) kata kerja arsyada – yursyidu yang berarti “membimbing, menunjuki (jalan yang lurus)”, terambil dari kata rasyad ‘hal memperoleh petunjuk/kebenaran’ atau rusyd dan rasyada ‘hal mengikuti jalan yang benar/lurus’ [Lisan al-Arab, juz III: 175-176].
Dengan demikian, makna mursyid adalah “(orang) yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus” Dalam wacana tasawuf/tarekat mursyid sering digunakan dengan kata Arab Syaikh; kedua-duanya dapat diterjemahkan dengan “guru”.
Dalam al-Quran kata mursyid muncul dalam konteks hidayah (petunjuk) yang dioposisikan dengan dhalalah (kesesatan), dan ditampilkan untuk menyipati seorang wali yang oleh Tuhan dijadikan sebagai khalifah-Nya untuk memberikan petunjuk kepada manusia:
‘Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia benar-benar mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, maka orang itu tidak akan pernah engkau dapati memiliki wali mursyid (pemimpin yang mampu memberi petunjuk).” (Al-Kahfi :17)
Kata wali (jamak: awliya) sendiri menunjukan kepada beberapa makna, antara lain al-nashir ‘penolong’ [Lisan al-Arab, XV: 406], al-mawla fi al-din ‘pemimpin spiritual’[Lisan al-Arab juz XV: 408], al-shadiq ‘teman karib’ dan al-tabi al-muhibb ‘pengikut yang mencintai’ [Lisan al-Arab, juz XV:411] Semua makna ini berserikat dan secara simultan menjelaskan makna wali dalam ayat diatas, yaitu “orang yang mencintai dan dicintai Allah sehingga layak menjadi pemimipin spritual yang harus diikuti”.
Pengertian wali semacam ini digambarkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan beberapa imam hadis lainnya dengan redaksi:
“Barangsiapa memusuhi seorang wali-Ku, maka Aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai berupa ibadah-ibadah yang Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku itu terus menerus mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah, kecuali Aku pasti dengannya ia mendengar, (Akulah) matanya yang dengannya ia melihat, (Akulah) tangannya yang dengannya ia melakukan sesuatu, dan (Akulah) kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku niscaya Aku mengabulkannya; dan jika ia memohon perlindungan kepada-Ku niscaya Aku melindunginya [Shahih al-Bukhari, V: 2384; Shahih Ibn Hibban, II: 58; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, juz III: 346].
Menurut berbagai riwayat yang sahih, wali-wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang memiliki karakteristik utama “tidak pernah lepas dari berdzikir kepada Allah” sebagaimana halnya Nabi saw yang oleh ‘Aisyah dengan “selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap detik yang beliau milik” (kana yadzkurullaha fi kulli ahyanihi) [Musnad Abi Ya’la, juz VIII: 355]. Imam al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir-nya meriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Sesungguhnya di antara manusia ada kunci-kunci dzikrullah; apabila mereka dilihat orang maka (yang melihat) itu langsung berdzikir kepada Allah” [Al-Mu’jam al-Kabir, juz X:205].
Maksud “kunci-kunci dzikrullah” dalam riwayat tersebut adalah wali-wali Allah sesuai dengan hadis dalam riwayat Ibn Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah saw ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah wali-wali Allah itu? Beliau menjawab:
“Orang-orang yang apabila mereka dilihat orang maka orang (yang melihat) itu berdzikir kepada Allah karena melihat mereka” [ Mushaannaf Ibn Abi Syaibah, juz VII: 79; Musnad al-Bazza,juz VII: 158].
Imam al-Tirmidzi juga meriwayatkan:
"Nabi Musa as pernah bertanya kepada Tuhannya, “Tuhan, siapakah wali-wali-Mu?” Tuhan menjawab:“Orang-orang yang apabila mereka berdzikir engkau pun berdzikir dan apabila engkau berdzikir mereka pun berdzikir” Nawadir al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, juz IV: 86].
Imam al-Suyuthi mengutip sebuah riwayat yang menceritakan bahwa kaum Hawariyyun bertanya kepada Nabi Isa as, “Siapa wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih?” Nabi Isa menjawab:“Orang-orang yang memandang hakikat dunia sementara manusia memandang permukaannya, dan orang-orang yang memandang dunia yang abadi (akhirat) sementara manusia memandang dunia yang fana” [Tafsir al-Durr al-Mantsur, juz IV: 370].
Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang yang bukan nabi dan bukan pula syuhada’ tetapi pada hari kiamat para Nabi dan syuhada’ menginginkan seperti mereka karena kedudukan mereka disisi Allah ‘azza wa jalla.”
Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa mereka dan apa amal-amal mereka? Boleh jadi kami akan mencintai mereka.” Rasulullah bersabda , “Mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan ruh Allah tidak atas dasar hubungan darah antara mereka dan tidak pula atas dasar harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, wajah mereka adalah nur (Allah) dan mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur; mereka tidak takut ketika orang lain takut”. Kemudian Rasulullah membacakan ayat “Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih (Q.S. Yunus,:62).” Hadis tersebut dikutip oleh Imam al-Jauzi dari jalur ‘Umar Ibn al-Khaththab r.a. dalam Zad al-Masir-nya, [Zad al-Masir, juz IV: 43-44], dan dikutip juga oleh Imam Ibn Hibban dalam Shahih-nya [Shahih Ibn Hibbam juz II: 332], dan oleh Imam al-Bayhaqi dalam al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab [al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab, juz I:134], dari jalur Abu Hurairah.
Mursyid sebagai Pemandu Jalan
Mursyid dalam thariqah adalah seorang wali yang layak diikuti sebagai imam dalam perjalanan menuju Tuhan. Ia adalah wali Allah yang ciri khasnya sebagaimana disebutkan di atas. Jalan menuju Tuhan bukan jalan yang mulus melainkan jalan yang berliku-liku dan penuh dengan rintangan-rintangan berupa ranjau-ranjau Iblis sehingga diperlukan pemandu yang arif untuk bisa selamat dari semua rintangan itu. Seorang salik, orang yang menempuh perjalanan (menuju Tuhan) atau yang biasa disebut dengan murid, yang telah membulatkan kehendaknya untuk menempuh perjalanan (menuju Tuhan) tidak boleh tidak harus didampingi mursyid sebagai pemandu jalan yang menuntun dan sekaligus memperingatkannya apabila ada bahaya yang mengancam. Keberadaan seorang mursyid dengan fungsi ini sangat mutlak.
Barang siapa berjalan tanpa pemandu, ia memerlukan dua ratus tahun untuk perjalanan dua hari, kata Jalaluddin Rumi dalam Matsnawi yang dikutip oleh Annemarie Schimmel [Dimensi Mistik dalam Islam, hal. 106], untuk menggambarkan betapa sulitnya perjalanan itu dan betapa pentingnya keberadaan seorang pemandu (mursyid).
Posisi mursyid atau syaikh sufi menurut Ibn Taimiyah tidak ubahnya seperti imam dalam shalat dan pemandu haji (dalil-al-hajj); imam shalat diikuti oleh makmum, mereka shalat sesuai dengan shalatnya imam (yushalluna bi shalatihi), sedangkan pemandu haji menunjukan kepada jamaah jalan menuju baitullah (yadullu al-wafd ala thariq al-bait)[ Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, VIII: 49].
Dalam peristiwa Isra dan Miraj (perjalanan Nabi menuju Tuhan), Nabi saw dipandu oleh Jibril as yang berfungsi sebagai mursyid, imam atau guide, yaitu pemandu jalan yang menuntun dan membimbing beliau hingga sampai di hadirat Allah ‘azza wa jalla.
Dalam Tafsir al-Thabari disebutkan bahwa dalam Miraj itu, Nabi saw bertemu dengan seorang tua renta di sisi jalan, dan ketika beliau bertanya siapa orang itu, Jibril as. berkata, Teruslah berjalan, wahai Muhammad (sir ya muhammad)!
Beliau juga mendengar sebuah suara yang menyeru beliau agar menyingkir dari jalan, “Halumma ya muhammad, ke sinilah Muhammad!, sebelum Nabi saw sempat menoleh Jibril sudah langsung memperingatkan, Teruslah berjalan, wahai muhammad (sir ya muhammad)!
Beberapa saat kemudian Jibril memberikan penjelasan. Orang tua yang engkau lihat di sisi jalan tadi menunjukan bahwa tidak tersisa dari dunia ini kecuali sekadar sisi umur orang tua itu, sedangkan suara yang hendak memalingkanmu adalah Iblis [Tafsir al-Thabari, juz XV: 6; Tafsir Ibn Katsir, juz III: 6 Al-Ahadits al-Mukhtarah, juz VI: 258].
Peristiwa Isra dan Miraj Nabi saw memang menjadi rujukan utama para sufi, terutama yang berkenaan dengan unsur Jibril as. yang berfungsi sebagai mursyid, sang pemandu.
Keberadaan unsur Jibril as sangat mutlak sedemikian rupa sehingga andaikata unsur ini tidak ada, maka Nabi saw akan terperangkap oleh jebakan Iblis. Lalu bagaimana dengan umat beliau? Apakah mereka juga memerlukan unsur Jibril ini? Jawabannya pasti: ya, tidak boleh tidak. Posisi dan fungsi unsur Jibril ini justru diduduki dan dilaksanakan oleh Nabi sendiri.
Urgensi unsur Jibril sangat jelas terutama mengingat pernyataan Nabi saw bahwa shalat adalah miraj-nya orang mukmin [Syarh Sunan Ibn Majah, hal. 313]. Artinya, orang-orang mukmin juga dimungkinkan mengalami miraj dengan izin dan kehendak Tuhan. Sebagai sarana miraj, dalam shalat seorang mukmin harus melibatkan unsur Jibril; kalau tidak, maka shalatnya akan didominasi oleh unsur setan, sehingga shalat itu menjadi shalat yang tanpa makna, gersang, dan jauh dari nilai-nilai khusyuk, yang pada gilirannya tidak dapat berfungsi sebagai tanha an al-fahsya wa al-munkar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar [al-Ankabut :45].
Shalat semacam ini kata Nabi saw dalam riwayat al-Thabrani dengan perawi-perawi sahih [Majma al-Zawaid, juz II: 258], adalah shalat yang hanya akan menjauhkan pelakunya dari Allah SWT (man lam tanhahu shalatuhu an al-fahsya wa al-munkar lam yazdad minallahi illa budan), [Al-Mu’jam al-Kabir, juz XI: 54]. Berbagai kasus dalam kehidupan orang-orang mukmin menjadi bukti tak terbantah atas pernyataan ini.
Miraj adalah karunia Tuhan yang berupa perjalanan menuju Dia SWT dengan perbentangan berbagai fenomena ghaib (metafisik) sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.
Dalam sejarah Nabi saw dikenal dua jenis miraj: Khusus dan umum.
Miraj khusus dialami Nabi saw pada saat beliau menerima perintah shalat wajib lima waktu, sedangkan miraj umum dialami Nabi saw pada saat-saat yang lain termasuk ketika beliau dimuliakan Allah dengan diangkat sebagai rasul.
Dalam wacana sufi miraj umum lebih sering disebut dengan istilah muraqabah, dan sangat dimungkinkan dialami oleh siapa pun dari kalangan orang-orang beriman. Pengalaman melihat sorga dan neraka dengan mata kepala (muraqabah) yang dialami para sahabat merupakan indikasi nyata atas kemungkinan ini.
Dalam kitab Shahih-nya Imam Muslim memuat bab yang menyinggung soal muraqabah; di dalamnya diriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Hanzhalah al-Usayyidi, salah seorang sekretaris Rasulullah saw; ia berkata bahwa ketika Nabi bercerita tentang sorga dan neraka, ia dan Abu Bakar ra. merasa melihat sorga dan neraka itu dengan mata kepala mereka, tetapi masing-masing dari mereka banyak yang lupa apa yang mereka lihat, lalu mereka memutuskan untuk menghadap Nabi saw dan menanyakan hal itu. Dialog antara Hanzhalah dan Nabi dapat disimak dari kutipan berikut:
Aku (Hanzhalah) berkata, Hanzhalah telah munafik, wahai Rasulullah. Rasulullah saw bertanya, Ada apa?. Aku (Hanzhalah) berkata, Wahai Rasulullah, kami pernah berada di hadapanmu mendengarkan engkau bercerita kepada kami tentang sorga dan neraka sehingga kami seolah-olah melihat sorga dan neraka itu dengan mata kepala. Setelah kami pulang dari hadapanmu, serta bertemu dan bermain-main dengan anak-istri kami dan pergi keperkarangan kami, kami banyak lupa tentang hal itu. Rasulullah saw bersabda, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kalian berkekalan dengan apa yang kalian lihat dihadapanku dan berkekalan dalam dzikir, niscaya para malaikat menjabat tangan kalian diatas tempat tidur kalian dan dijalan-jalan (tarekat-tarekat) kalian. Sayangnya, wahai Hanzhalah, (muraqabah itu) hanya sesaat dan sesaat (ini diucapkan tiga kali oleh beliau)” [Shahih Muslim, juz IV: 2106; Musnad Ahmad, juz IV: 346; Sunan al-Tirmidzi, juz IV: 666].
Dalam kasus tersebut para sahabat telah mengalami muraqabah dan sekaligus miraj, karena miraj pada dasarnya dapat dipahami sebagai naik dan melintasi alam fisik, keluar dari dimensi ruang dan waktu, serta memasuki dan menyaksikan alam metafisik ketuhanan. Pengalaman miraj para sahabat tersebut terjadi berkat bimbingan Rasul saw sebagai pemandu, sebagaimana Rasul sendiri mengalami miraj berkat bimbingan Jibril as. dengan izin Allah SWT. Dengan kata lain, mereka dibawa miraj oleh Nabi saw sebagaimana Nabi dibawa miraj oleh Jibril as. dengan izin Allah. (Lalu, bagaimana dengan orang-orang mukmin lain yang tidak bertemu dengan Nabi? Siapa yang akan membawa mereka miraj?!).
Hikmah yang dapat diambil dari pengalaman itu adalah bahwa yang bersangkutan pasti menyadari secara haqqul yaqin bahwa ungkapan al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun (kami milik Allah dan kepada-Nya kami pulang) [Al-Baqarah :156] adalah benar (haqq), dan bahwa mereka ketika hidup di dunia pada hakikatnya sedang berada dalam perjalanan pulang menuju Tuhan, sebuah perjalanan yang sangat sulit dan berliku-liku.
Dengan adanya seorang pemandu, perjalanan itu akan terasa lebih ringan, mudah, dan lancar sehingga tepat sekali ungkapan Rumi yang dikutip sebelumnya, Barangsiapa berjalan tanpa pemandu, ia memerlukan dua ratus tahun untuk perjalanan dua hari.
Mursyid sebagai Khalifah Rasul
Imam-imam hadis, selain al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan sebuah hadis perpisahan yang didalamnya antara lain Nabi saw bersabda:
Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa al-rasyidun yang memperoleh petunjuk; berpeganglah kepada sunnah-sunnah itu dan ‘gigitlah’ sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian [Shahih Ibn Hibban, juzI: 179; sunan al-Tirmidzi, juz V: 44; Sunan Abi Dawud, juz IV: 200; Sunan Ibn Majah, juz I: 16; Sunan al-Baihaqi al-Kubra, juz X:114].
Dalam hadis itu tampak bahwa sunnah Nabi saw disandingkan dengan sunnah para khalifah (pengganti) beliau; kedua jenis sunnah ini sama-sama wajib diikuti dan dipegangi secara teguh oleh setiap mukmin. Ini menunjukan bahwa sunnah al-khulafa al-rasyidun adalah sunnah yang suci sebagaimana Sunnah Nabi saw sendiri. Tidak mungkin Nabi saw memerintahkan mengikuti sunnah mereka apabila sunnah itu mengandung cacat atau hal-hal yang bertentangan dengan syara.
Siapakah sesungguhnya yang dimaksud dengan al-khulaf al-rasyidun itu? Selama ini ungkapan al-khulafa al-rasyidun dipahami sebagai pengganti Nabi saw di bidang politik, yaitu sebagai kepala negara/pemerintahan Islam yang bertanggung jawab atas semua urusan politik umat. Mereka adalah Abu Bakar al-Shiddiq ra., Umar Ibn al-Khaththab ra., Utsman Ibn Affan ra., dan Ali Ibn Abi Thalib ra.
Belakangan nama Amirul Mukminin Umar Ibn Abd al-Aziz ra diposisikan sebagai khalifah kelima dan sekaligus terakhir dari al-khulafa al-rasyidun, sehingga secara keseluruhannya al-khulafa al-rasyidun dalam pengertian ini hanya berjumlah lima orang. Tetapi di samping pengertian sebagai pengganti Nabi saw di bidang politik, pengertian al-khulafa al-rasyidun juga dapat ditinjau dari segi spiritual, sebab Nabi saw tidak sekedar sebagai kepala negara/pemerintahan melainkan juga sebagai Nabi dan Rasul yang membawa misi tauhid dan ubudiah serta penyempurnaan akhlak yang mulia.
Beliau adalah pemimpin spiritual yang oleh al-Quran digambarkan memiliki tugas-tugas:
(1) membacakan kepada umat ayat-ayat Tuhan, (2) menyucikan kalbu mereka, serta (3) mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah [Ali Imran : 164].
Tugas-tugas seorang khalifah sudah sepatutnya sesuai dengan tugas-tugas Nabi saw sebagai seorang Rasul, yaitu ta’lim (mengerjakan al-Kitab dan al-Hikmah) dalam kerangka tauhid, ubudiah, dan penyempurnaan akhlak yang mulia. Dengan pengertian kedua ini, al-khulafa al-rasyidun pada dasarnya menunjuk kepada ulama yang oleh Nabi SAW. diposisikan sebagai waratsah al-anbiya (ahli waris para Nabi), dan satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa Nabi saw atau Nabi-Nabi lainnya tidak mewariskan dinar atau dirham; mereka hanya mewariskan al-ilm (ilmu) [Musnad Ahmad, V: 196; Shahih al-Bukhari, I: 46]. Mereka itulah hamba-hamba pilihan yang kepada mereka Allah mewariskan al-Quran [Fathir, 35:32], sehingga mereka disebut dengan ahl al-dzikr yang kepada mereka setiap orang harus bertanya [Al-Nahl, :43; al-Anbiya, :7].
Ciri khas mereka adalah bahwa mereka tidak pernah meminta upah atas upaya dakwah mereka karena Nabi saw juga tidak meminta upah atas dakwah beliau [Yusuf : 104]; dan Allah memerintahkan agar mengikuti orang-orang yang tidak pernah meminta upah seperti mereka [Yasin :21, Al Furqan :57].
Dengan warisan ciri khas semacam ini mereka layak menyandang gelar khalifah (pengganti) Rasul yang sekaligus sebagai penegak hujjah Allah, dan jumlah mereka tentu tidak hanya lima orang meskipun juga tidak banyak.
Sebagai hamba-hamba pilihan Tuhan, jumlah mereka memang sedikit sebagaimana ditegaskan oleh sayyidina Ali Ibn Thalib r.a. ketika berkata kepada Kuhail ibn-Ziyad, Demi Allah, sungguh bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang menegakkan hujjah-hujjah Allah agar tanda-tanda kebesaran-Nya tidak hilang dan hujjah-Nya tidak terbantahkan. Mereka adalah orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit, namun sangat agung dan terhormat di sisi Allah.
Bahwa al-khulafa al-rasyidun yang dimaksud oleh Nabi saw lebih terkait dengan khalifah-khalifah spiritual daripada khalifah-khalifah di bidang politik dapat disimak pula dari kenyataan bahwa Umar Ibn al-Khaththab ra dan beberapa sahabat lainnya ternyata masih diperintahkan oleh Nabi saw agar menemui dan meminta syafaat kepada Uwais al-Qarni ra, seorang laki-laki dalam hadis riwayat Imam Muslim disebut sebagai khayr al-tabiin, orang terbaik di antara orang-orang yang hidup pada masa sahabat;
Sesungguhnya tabiin terbaik adalah seseorang yang bernama Uwais; dia hanya punya seorang ibu dan juga punya penyakit kusta; maka mintalah kepadanya agar ia memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian [Shahih Muslim, juz IV: 1968; Musnad Ahmad, juz I: 38].
Berkaitan dengan diri Uwais al-Qarni ra inilah, dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah r.a., disebutkan bahwa Nabi saw bersabda:
Iman ada di Yaman dan hikmah pun ada di Yaman (dalam riwayat lain ada tambahan: dan aku cium nafas al-rahman dari arah Yaman, atau, dan aku cium nafas Tuhanmu dari arah Yaman) [ Shahih al-Bukhari, III: 1289; Shahih Muslim, I: 72 dan Shahih Ibn Hibban, XVI: 288].
Nafas al-rahman yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah Uwais al-Qarni. Dia adalah wali Allah yang paling besar pada masanya; disembunyikan oleh Allah di tengah-tengah rakyat jelata sehingga orang-orang tidak mengetahuinya dan bahkan sering mengejeknya. Dia berasal dariku dan aku berasal darinya, kata Rasulullah saw [Al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab,juz I:113].
Ungkapan Rasul ini menunjukan kepada hubungan spiritual antara Uwais al-Qarni ra dan Nabi saw meskipun ia belum pernah bertemu dengan beliau.
Kualifikasi Mursyid
Dengan menyimak misi, tugas-tugas, dan ciri khas dakwah Rasulullah saw dan para khalifah (pengganti) beliau dapat dipahami bahwa tidak setiap ulama dapat serta-merta menjadi Mursyid terutama dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dan guru spiritual, karena diantara ulama ada pula bahkan banyak sekali yang sekedar berbaju ulama tetapi prilakunya justru bertentangan dengan esensi ulama itu sendiri, yaitu takut kepada Allah sebagaimana diisyaratkan al-Quran:
Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama (Fathir :28).
Di antara mereka banyak pula yang terbuai oleh harta dan kenikmatan duniawi; mereka tidak berdakwa kecuali upah yang akan diperolehnya sudah jelas. Ulama semacam ini oleh Imam al-Ghazali disebut dengan ulama dunia atau ulama su’ (jahat) :
Diantara perkara-perkara yang paling penting adalah mengetahui tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Yang dimaksud dengan ulama dunia disini adalah ulama su’ yang bertujuan mengejar kenikmatan dunia serta memburu kehormatan dan kedudukan di antara ahli ilmu [Ihya Ulum al-Din, juz I: 58].
Oleh karena itu ketika berbicara tentang kualifikasi seorang Mursyid, Imam al-Ghazali menjadikan kebebasan dari kecintaan terhadap harta dan kedudukan sebagai kriteria awal:
Mursyid adalah orang yang:
(1) dari batinnya sudah keluar kecintaan terhadap harta dan kedudukan;
(2) format pendidikannya berlangsung di tangan seorang Mursyid juga, dan begitulah seterusnya hingga silsilah itu berakhir pada Nabi saw;
(3) mengalami riyadhah (latihan jiwa) seperti sedikit makan, bicara, dan tidur, serta banyak melakukan salat, sedekah dan puasa;
(4) memperoleh cahaya dari cahaya-cahaya Nabi saw;
(5) terkenal kebaikan biografinya dan kemulian akhlaknya seperti sabar, syukur, tawakal, yakin, damai, dermawan, qanaah, amanah, lemah lembut, rendah hati, berilmu, jujur, berwibawa, malu, tenang, tidak tergesa-gesa, dan lain sebagainya;
(6) suci dari akhlaq yang tercela seperti sombong, kikir, dengki, tamak, berangan-angan panjang, gegabah dan lain sebagainya;
(7) bebas dari ekstremitas orang-orang yang ekstrem; dan
(8) kaya dengan ilmu yang diperoleh langsung dari Rasulullah saw sehingga tidak membutuhkan ilmu orang-orang yang mengada-ada (ilm al-mukallafin) [Khulashah al-Tashanif al-Tashawwuf dalam Majmu Rasail al-Imam al-Ghazali, hal. 173].
Sedikit berbeda dari Imam al-Ghazali, al-Mukarram Saidi Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengumumkan kualifikasi sebagai berikut:
1. Pilih Guru yang Mursyid, dicerdikan oleh Allah SWT, bukan dicerdikan oleh yang lain-lain, dengan izin dan ridha Allah, karena Allah.
2. Yang kamil mukamil (sempurna dan menyempurna), diberi karunia oleh Allah, karena Allah.
3. Yang memberi bekas pengajarannya, (kalau ia mengajar atau mendoa berbekas pada si murid, si murid berobah kearah kebaikan), berbekas pengajarannya itu, dengan izin dan ridha Allah, biidznillah.
4. Yang masyhur kesana kemari, kawan dan lawan mengatakan, ia seorang Guru Besar.
5. Yang tidak dapat dicela oleh orang yang berakal akan pengajarannya, yaitu tidak dapat dicela oleh hadits dan Qur’an dan oleh ilmu pengetahuan (tidak bersalah-salahan dengan hadits, Qur’an dan akal).
6. Tidak setengah kasih kepada dunia, karena bulatnya hatinya, kasih kepada Allah. Ia ada giat bergelora dalam dunia, bekerja hebat dalam dunia, tetapi bukan karena kasih kepada dunia itu, tetapi karena prestasinya itu adalah sebagai abdinya kepada Allah SWT dalam hidupnya.
7. Mengambil ilmu dari orang yang tertentu; Gurunya harus mempunyai tali yang nyata kepada Allah dan Rasul dengan silsilah yang nyata [Ibarat Sekuntum Bunga dari Taman Firdaus, hal. 173].
Wasilah (Nurun ‘ala Nurin)
Ungensi posisi Mursyid yang sangat penting dalam thariqah sebagai jalan menuju Tuhan sebenarnya erat kaitannya dengan masalah wasilah yang oleh Allah diperintahkan agar orang-orang mukmin mencarinya:
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (yang menyampaikanmu) kepada Allah, serta berjuanglah di jalan-Nya, agar kamu menang. (al-Maidah :35)
Dari uraian-uraian berikut akan dipahami bahwa Mursyid adalah pembawa wasilah sebagaimana Jibril adalah pembawa Buraq yang oleh Imam Zubaidi disebut sebagai kendaraan para nabi [Syarh al-Nawawi Shahih Muslim, juz II: 210]
BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM IBADAH
Tahukah kita, jantung yang ada dalam tubuh adalah alat pemompa yang amat menakjubkan. la bekerja terus tanpa henti sejak minggu ke-4 dari kehidupan manusia (di dalam rahim) hingga kernatiannya. Jika seseorang berumur 60 tahun, berarti selama itulah jantungnya tidak pernah berhenti bekerja memompa darah. Adakah pompa di dunia ini yang tahan bekerja selama 60 tahun tanpa henti?.
Jantung manusia beratnya tidak lebih dari 250 gram. la berdenyut 70 kali permenit atau 100 ribu kali perhari. la menyemprotkan darah sebanyak 5 liter permenit atau 1.5 juta gal lon pertahun—meskipun darah yang disemprotkan adalah yang itu-itu juga. Alat pemompa yang menakjubkan ini mengirimkan darah ke selaput nadi, urat syaraf, dan pembuluh darah, yang jika semua itu diletakkan secara berurutan pada sebuah garis lurus maka panjangnya bisa mencapai 60-100 ribu mil!.
Tahukah kita, Galaksi Bimasakti hanyalah salah satu galaksi (gugusan bintang) di dalam sistem tatasurya kita. Galaksi Bimasakti terdiri dari sekitar 200 miliar bintang. Para astronom memperkirakan bahwa di alam raya ini terdapat miliaran galaksi, dengan sekitar 1.000 triliun planet dan bintang. Setiap bintang atau galaksi berjalan pada orbitnya dengan kecepatan kira-kira 65.000 km perdetik. Di antara bintang-bintang itu ada yang berukuran ribuan kali besar matahari, yang jaraknya dari bumi adalah jutaan tahun cahaya. Satu tahun cahaya kira-kira 9.416 miliar km atau sekitar 10.000 tahun!. Itulah di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Itulah ayat-ayat kauniyyah-Nya. Semua ayat-ayat kauniyyah itu pada akhirnya meneguhkan klaim Allah SWT sendiri:
Tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan main-main (QS al-Anbiya' [21]: 16). Benar, Allah SWT tidak pernah bermain-main. Sebagaimana kata Einstein, Tuhan tidak sedang bermain dadu ketika menciptakan jagat raya ini. Artinya, Allah menciptakan seluruh jagad raya ini dengan sungguh-sungguh.
Allah SWT juga tentu tidak main-main ketika menurunkan ayat-ayat qawliyyah-Nya., yakni al-Quran. Al-Quran tidak lain adalah kalam (firman) Allah, Zat Yang Mahakuasa. Di dalamnya tidak secuil pun cacat-cela, yang membuktikan bahwa al-Quran— sebagaimana klaim-Nya—benar-benar berasal dari sisi-Nya:
”Tidakkah kalian memperhatikan al-Quran? Seandainya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka bakal menjumpai banyak pertentangan di dalamnya” (QS an-Nisa' [4]: 82).
Jika Allah tidak pernah main-main dengan ayat-ayat kauniyyah-Nya. (penciptaan alam semesta), juga dengan ayat-ayat qawliyyah-Nya. (al-Quran), kita mendapati manusia malah sering 'bermain-main' dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Ketika Allah tidak pernah main-main menciptakan jagad raya ini, termasuk manusia, kita mendapati banyak manusia justru sering 'bermain-main' dengan kehidupannya; tidak serius dan bersungguh-sungguh menjalani tugasnya sebagai hamba Allah, yakni beribadah kepada-Nya dalam makna yang seluas-luasnya. Padahal bukankah ibadah (pengabdian kepada Allah) merupakan raison d'etre penciptaan manusia? Allah SWT berfirman:
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS adz-Dzariyat [51]: 56).
Sebagai Muslim, kita tentu patut meneladani Nabi Muhammad saw. dan para Sahabatnya, yang senantiasa menjalani kehidupan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, tanpa pernah bermain-main; terutama dalam urusan ibadah, dakwah, dan jihad. Dalam urusan ibadah, kita tahu, Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling banyak melakukannya. Nabi saw. tidak pernah meninggalkan shalat malam, bahkan hingga kakinya sering bengkak-bengkak karena lamanya berdiri ketika shalat. Nabi pun orang yang paling banyak berpuasa, bahkan puasa wishal, karena begitu seringnya Beliau tidak menjumpai makanan di rumahnya. Nabi juga adalah orang yang paling banyak bertobat, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari, padahal Beliau adalah orang yang ma 'shum (terpelihara dari dosa) dan dijamin masuk surga.
Meski tidak sehebat Nabi saw., para Sahabat adalah orang-orang yang paling istimewa ibadahnya setelah Beliau, tidak ada yang melebihi mereka. Mereka, misalnya, adalah orang-orang yang pal ing banyak mengkhatamkan al-Quran, paling tidak sebulan sekali, bahkan ada yang kurang dari itu. Menurut Utsman bin Affan ra., banyak Sahabat yang mengkhatamkan al-Quran seminggu sekali. Mereka antara lain Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Kaab, dan Zaid bin Tsabit. Ustman ra. sendiri sering mengkhatamkan al-Quran hanya dalam waktu semalam. Itu sering ia lakukan dalam shalat malam.
Semua itu menunjukkan bahwa Nabi saw. dan para Sahabat adalah orang-orang yang senantiasa serius dan bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah; mereka tidak pernah main-main.
Bagaimana dengan dakwah mereka? Jangan ditanya. Nabi saw. dan para Sahabat adalah orang-orang yang telah menjadikan dakwah sebagai jalan hidup sekaligus 'jalan kematian' mereka. Dengan kata lain, mereka hidup dan mati untuk dakwah. Sebagian besar usia mereka, termasuk harta dan jiwa mereka, diwakafkan di jalan dakwah demi menegakkan kalimat-kalimat Allah.
Bagaimana dengan jihad mereka? Para Sahabat, sebagaimana sering diungkap, adalah orang-orang yang mencintai kematian (di jalan Allah) sebagaimana orang-orang kafir mencintai kehidupan. Amr bin Jamuh hanyalah salah seorang Sahabat, di antara ribuan Sahabat, yang mencintai kematian itu.
Dikisahkan, ia adalah orang yang sering dihalang-halangi untuk berjihad oleh saudara-saudaranya karena kakinya pincang. Rasul pun telah membolehkan-nya untuk tidak ikut berjihad karena 'udzur-nya. itu. Namun, karena keinginan dan kecintaannya yang luar biasa pada syahadah (mati syahid), ia terus mendesak Rasul agar mengizinkannya berperang. Akhirnya, Rasul pun mengizinkannya. Dengan penuh kegembiraan, Amr pun segera berlari menuju medan perang, berjibaku dengan gigih melawan musuh, hingga akhirnya terbunuh sebagai syahid.
Itulah secuil fragmen keseriusan dan kesungguhan salafusshalih dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita serius dan bersungguh-sungguh dalam hidup ini? Ataukah kita masih mengisi hidup ini dengan main-main? Na'udzu billah min dzalik
Jantung manusia beratnya tidak lebih dari 250 gram. la berdenyut 70 kali permenit atau 100 ribu kali perhari. la menyemprotkan darah sebanyak 5 liter permenit atau 1.5 juta gal lon pertahun—meskipun darah yang disemprotkan adalah yang itu-itu juga. Alat pemompa yang menakjubkan ini mengirimkan darah ke selaput nadi, urat syaraf, dan pembuluh darah, yang jika semua itu diletakkan secara berurutan pada sebuah garis lurus maka panjangnya bisa mencapai 60-100 ribu mil!.
Tahukah kita, Galaksi Bimasakti hanyalah salah satu galaksi (gugusan bintang) di dalam sistem tatasurya kita. Galaksi Bimasakti terdiri dari sekitar 200 miliar bintang. Para astronom memperkirakan bahwa di alam raya ini terdapat miliaran galaksi, dengan sekitar 1.000 triliun planet dan bintang. Setiap bintang atau galaksi berjalan pada orbitnya dengan kecepatan kira-kira 65.000 km perdetik. Di antara bintang-bintang itu ada yang berukuran ribuan kali besar matahari, yang jaraknya dari bumi adalah jutaan tahun cahaya. Satu tahun cahaya kira-kira 9.416 miliar km atau sekitar 10.000 tahun!. Itulah di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Itulah ayat-ayat kauniyyah-Nya. Semua ayat-ayat kauniyyah itu pada akhirnya meneguhkan klaim Allah SWT sendiri:
Tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan main-main (QS al-Anbiya' [21]: 16). Benar, Allah SWT tidak pernah bermain-main. Sebagaimana kata Einstein, Tuhan tidak sedang bermain dadu ketika menciptakan jagat raya ini. Artinya, Allah menciptakan seluruh jagad raya ini dengan sungguh-sungguh.
Allah SWT juga tentu tidak main-main ketika menurunkan ayat-ayat qawliyyah-Nya., yakni al-Quran. Al-Quran tidak lain adalah kalam (firman) Allah, Zat Yang Mahakuasa. Di dalamnya tidak secuil pun cacat-cela, yang membuktikan bahwa al-Quran— sebagaimana klaim-Nya—benar-benar berasal dari sisi-Nya:
”Tidakkah kalian memperhatikan al-Quran? Seandainya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka bakal menjumpai banyak pertentangan di dalamnya” (QS an-Nisa' [4]: 82).
Jika Allah tidak pernah main-main dengan ayat-ayat kauniyyah-Nya. (penciptaan alam semesta), juga dengan ayat-ayat qawliyyah-Nya. (al-Quran), kita mendapati manusia malah sering 'bermain-main' dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Ketika Allah tidak pernah main-main menciptakan jagad raya ini, termasuk manusia, kita mendapati banyak manusia justru sering 'bermain-main' dengan kehidupannya; tidak serius dan bersungguh-sungguh menjalani tugasnya sebagai hamba Allah, yakni beribadah kepada-Nya dalam makna yang seluas-luasnya. Padahal bukankah ibadah (pengabdian kepada Allah) merupakan raison d'etre penciptaan manusia? Allah SWT berfirman:
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS adz-Dzariyat [51]: 56).
Sebagai Muslim, kita tentu patut meneladani Nabi Muhammad saw. dan para Sahabatnya, yang senantiasa menjalani kehidupan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, tanpa pernah bermain-main; terutama dalam urusan ibadah, dakwah, dan jihad. Dalam urusan ibadah, kita tahu, Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling banyak melakukannya. Nabi saw. tidak pernah meninggalkan shalat malam, bahkan hingga kakinya sering bengkak-bengkak karena lamanya berdiri ketika shalat. Nabi pun orang yang paling banyak berpuasa, bahkan puasa wishal, karena begitu seringnya Beliau tidak menjumpai makanan di rumahnya. Nabi juga adalah orang yang paling banyak bertobat, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari, padahal Beliau adalah orang yang ma 'shum (terpelihara dari dosa) dan dijamin masuk surga.
Meski tidak sehebat Nabi saw., para Sahabat adalah orang-orang yang paling istimewa ibadahnya setelah Beliau, tidak ada yang melebihi mereka. Mereka, misalnya, adalah orang-orang yang pal ing banyak mengkhatamkan al-Quran, paling tidak sebulan sekali, bahkan ada yang kurang dari itu. Menurut Utsman bin Affan ra., banyak Sahabat yang mengkhatamkan al-Quran seminggu sekali. Mereka antara lain Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Kaab, dan Zaid bin Tsabit. Ustman ra. sendiri sering mengkhatamkan al-Quran hanya dalam waktu semalam. Itu sering ia lakukan dalam shalat malam.
Semua itu menunjukkan bahwa Nabi saw. dan para Sahabat adalah orang-orang yang senantiasa serius dan bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah; mereka tidak pernah main-main.
Bagaimana dengan dakwah mereka? Jangan ditanya. Nabi saw. dan para Sahabat adalah orang-orang yang telah menjadikan dakwah sebagai jalan hidup sekaligus 'jalan kematian' mereka. Dengan kata lain, mereka hidup dan mati untuk dakwah. Sebagian besar usia mereka, termasuk harta dan jiwa mereka, diwakafkan di jalan dakwah demi menegakkan kalimat-kalimat Allah.
Bagaimana dengan jihad mereka? Para Sahabat, sebagaimana sering diungkap, adalah orang-orang yang mencintai kematian (di jalan Allah) sebagaimana orang-orang kafir mencintai kehidupan. Amr bin Jamuh hanyalah salah seorang Sahabat, di antara ribuan Sahabat, yang mencintai kematian itu.
Dikisahkan, ia adalah orang yang sering dihalang-halangi untuk berjihad oleh saudara-saudaranya karena kakinya pincang. Rasul pun telah membolehkan-nya untuk tidak ikut berjihad karena 'udzur-nya. itu. Namun, karena keinginan dan kecintaannya yang luar biasa pada syahadah (mati syahid), ia terus mendesak Rasul agar mengizinkannya berperang. Akhirnya, Rasul pun mengizinkannya. Dengan penuh kegembiraan, Amr pun segera berlari menuju medan perang, berjibaku dengan gigih melawan musuh, hingga akhirnya terbunuh sebagai syahid.
Itulah secuil fragmen keseriusan dan kesungguhan salafusshalih dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita serius dan bersungguh-sungguh dalam hidup ini? Ataukah kita masih mengisi hidup ini dengan main-main? Na'udzu billah min dzalik
Selasa, 10 Agustus 2010
AQIDAH ULAMA' EMPAT MADZHAB (ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN ARAH)
Bismillah
1. Imam Abu Hanifah ra. mengatakan bahwa kata Istiwa sudah dipahami. Bahkan Imam Abu Hanifah menolak mereka yang berpahaman Tajsim dan Tasybih sebagaimana tertuang dalam kitab beliau Fiqh al Akbar:
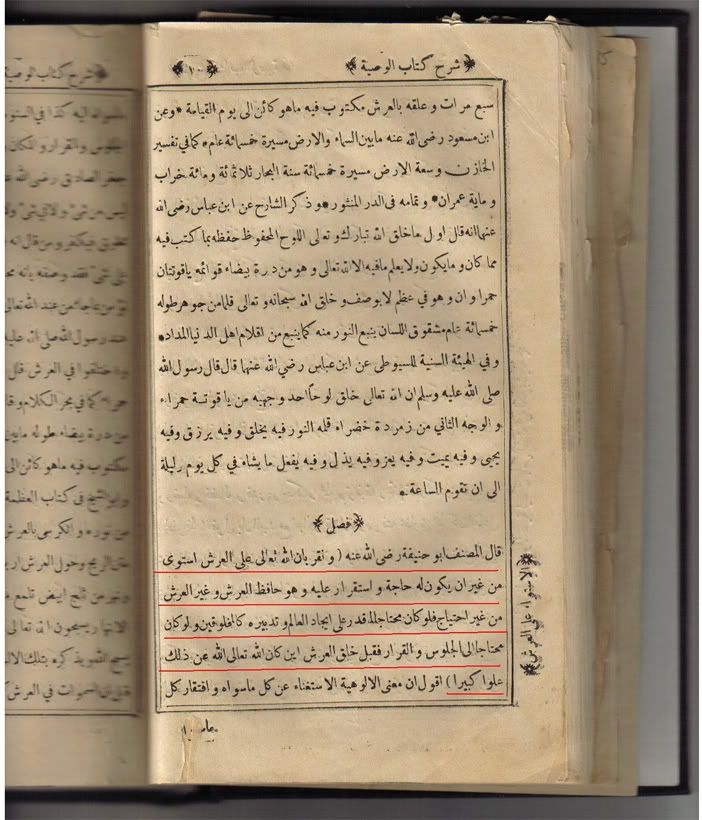
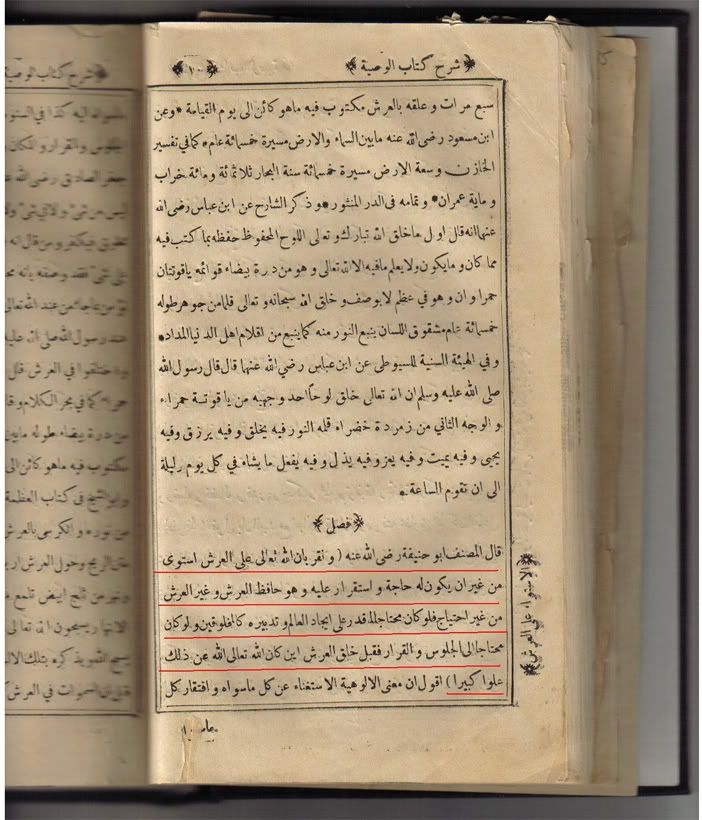
Berkata Imam Abu Hanifah: “Dan kami ( ulama Islam ) mengakui bahawa Allah ta’ala ber-istawa atas Arasy tanpa Dia memerlukan kepada Arasy dan Dia tidak metetap di atas Arasy, Dialah menjaga Arasy dan selain Arasy tanpa memerlukan Arasy, sekiranya dikatakan Allah memerlukan kepada yang lain sudah pasti Dia tidak mampu mencipta Allah ini dan tidak mampu mentadbirnya sepeti juga makhluk-makhluk, kalaulah Allah memerlukan sifat duduk dan bertempat maka sebelum diciptakan Arasy dimanakah Dia? Maha suci Allah dari yang demikian”
Amat jelas di atas bahwa akidah ulama Salaf sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah adalah menafikan sifat bersemayam(duduk) Allah di atas Arasy.
Semoga Mujassimah diberi hidayah sebelum mati dengan mengucap dua kalimah syahadah kembali kepada Islam.
2. Imam Syafi’i
انه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفته الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لايجوز عليه التغيير
انه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفته الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لايجوز عليه التغيير
Artinya: Sesungguhnya Dia Ta’ala ada (dari azali) sementara tempat belum diciptakan, kemudian Allah mencipta tempat dan Dia tetap dengan sifatnya yang azali itu sebagaimana sebelum terciptanya tempat, tidak harus ke atas Allah perubahan. Dinuqilkan oleh Imam Al-Zabidi dalam kitabnya Ithaf al-Sadatil Muttaqin jilid 2 halaman 23
3-Imam Ahmad bin Hanbal :
-استوى كما اخبر لا كما يخطر للبشر
Artinya: Dia (Allah) istawa sebagaimana Dia khabarkan (di dalam al Quran), bukannya seperti yang terlintas di pikiran manusia. Dinuqilkan oleh Imam al-Rifa'i dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, dan juga al-Husoni dalam kitabnya Dafu’ syubh man syabbaha Wa Tamarrad.
وما اشتهر بين جهلة المنسوبين الى هذا الامام المجتهد من أنه -قائل بشىء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه
Artinya: dan apa yang telah masyhur di kalangan orang-orang jahil yang menisbahkan diri mereka pada Imam Mujtahid ini (Ahmad bin Hanbal) bahwa dia ada mengatakan tentang (Allah) berada di arah atau seumpamanya, maka itu adalah pendustaan dan kepalsuan atas namanya (Imam Ahmad) – Kitab Fatawa Hadisiah karya Ibn Hajar al- Haitami
4- Imam Malik :
الاستواء غير المجهول والكيف غير المعقول والايمان به واجب و السؤال عنه بدعة
Artinya: Kalimah istiwa’ tidak majhul (diketahui dalam al quran) dan kaif (bentuk) tidak diterima aqal, dan iman dengannya wajib, dan bertanya tentangnya bid’ah
Perhatikan : Imam Malik hanya menulis kata istiwa (لاستواء) bukan memberikan makna dhahir jalasa atau duduk atau bersemayam atau bertempat (istiqrar)…..
ALLAH ADA TANPA BUTUH TEMPAT DAN ARAH
ada hal yang dipaksakan oleh kaum wahhaby yang kurang memahami ayat2 mutasyabihat dan menetapkan bahwa Alloh bersemayam di atas Arsy/Langit diambil dari kalimat ‘istiwa ‘alal Arsy’. Jika itu memang pernyataannya dan i’tiqodnya, baiklah.....ana akan mengajukan 2 pertanyaan?
1. Adakah ‘Arsy dan Langit yang ‘dipaksakan’ untuk dijadikan tempat bagi dzat Alloh yang maha mulia -ahlus sunnah berlepas diri dari penetapan sesat demikian- sama qodim-nya dengan dzat Alloh?
2. Jika jawabannya ya, maka selesai. Kita tidak usah diskusi lagi. Jika jawabannya tidak, maka pertanyaan logis berikutnya adalah DIMANA ALLOH SUBHANA WA TA’ALA BERADA SEBELUM MAKHLUK BERNAMA ‘ARSY DAN LANGIT ADA?Adakah perubahan pada dzat Alloh dari sebelum adanya Arsy dan atau Langit dengan sesudah diciptakan keduanya? Adakah tempat lain bagi Alloh untuk bersemayam sebelum keduanya diciptakan? Na’udzubillahi min dzalik. Maka benarlah apa disabdakan Rasululloh shallallohu ‘alayhi wa aalihi wa sallam seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Bayhaqqi dan imam Ibn Jarud: Kaana Allohu wa lam yakun syai’un ghoiruh : Alloh telah ada sebelum yang lainnya ada. Artinya Alloh qodim jauh sebelum Arsy dan langit ada.
2. Jika jawabannya ya, maka selesai. Kita tidak usah diskusi lagi. Jika jawabannya tidak, maka pertanyaan logis berikutnya adalah DIMANA ALLOH SUBHANA WA TA’ALA BERADA SEBELUM MAKHLUK BERNAMA ‘ARSY DAN LANGIT ADA?Adakah perubahan pada dzat Alloh dari sebelum adanya Arsy dan atau Langit dengan sesudah diciptakan keduanya? Adakah tempat lain bagi Alloh untuk bersemayam sebelum keduanya diciptakan? Na’udzubillahi min dzalik. Maka benarlah apa disabdakan Rasululloh shallallohu ‘alayhi wa aalihi wa sallam seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Bayhaqqi dan imam Ibn Jarud: Kaana Allohu wa lam yakun syai’un ghoiruh : Alloh telah ada sebelum yang lainnya ada. Artinya Alloh qodim jauh sebelum Arsy dan langit ada.
Diciptakannya Arsy dan Langit bukanlah untuk tempat bagi dzat Alloh, melainkan sebagai manifestasi dari kemahakuasaanNYA. Alloh tidak berhajat dengan ruang dan waktu. Dzat Alloh tidak mengalami perubahan. Alloh juga tidak terpenjara oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah makhluk ciptaanNYA, maha suci dzat yang qodim dari bersifat butuh terhadap ciptaanNYA. Sejalan dengan ucapan imam Ali karromallohu wajhah : kaana Allohu wa laa makaan, wa huwa al aan ayna maa kaana. Yang artinya : Alloh ada tanpa tempat dan Dia ada sebagaimana dahulu ada (yakni tanpa tempat).
Wahhabi menggunakan dalil yang katanya dari para sahabat, tabi’in, tabiut tabi’in dlsb dan mengkalim bahwa mereka Ahlus Sunnah. Namun justru ulama Ahlus Sunnah membantahnya. Tidak ada satu pun ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan tempat bagi Alloh sebagaimana Wahhabi tetapkan.
Berikut saya tambahkan nukilan dari situs lain tentang hal ini dan kesesatan pemahaman Wahhabi terhadap Dzat Alloh. Untuk rujukan silakan [klik ini], jika ingin versi bahasa Indonesianya [ini]
Imam Abu Hanifah, salah satu ulama as-Salaf, mengatakan dalam Al-Fiqh al Absat: “Allah Ta’ala ada abadi tanpa tempat, dan Dia ada sebelum mencipta makhluk. Dia telah ada dan ketika tidak ada tempat, makhluk atau benda-benda. Dia adalah Pencipta segala sesuatu”
Imam al-Hafidh al-Bayhaqiyy mengatakan dalam bukunya, Al-Asma’u was-Sifat, hal. 400: “…. Apa yang disebut di akhir hadis adalah indikasi penolakan bahwa Allah memiliki tempat dan penolakan bahwa hamba menyerupai Allah, seberapa pun dia, baik dekat maupun jauh. Allah Ta’ala adalah Adh-Dhahir, sehingga benar untuk mengetahui-Nya dengan bukti-bukti. Allah adalah Al-Bathin, sehingga tidak benar jika Dia berada dalam suatu tempat.” Dia juga berkata, ” Beberapa dari sahabat kita menggunakan sebuah bukti untuk membantah adanya tempat bagi Allah dengan hadis Rasululla SAW: “Engkau adalah Adh-Dhahir dan tidak ada di atas-Mu, dan Engkau adalah Al-Batin dan tidak ada yang di bawah-Mu”. Dengan demikian, jika tidak ada yang di atas dan di bawah Dia, Dia tidaklah di suatu tempat.”
Imam Ahmad Ibn Salamah, Abu Ja^far at Tahawiyy, (lahir 237 H),menulis buku Al-^Aqidah at Tahawiyyah. Dia menyebut bahwa isi bukunya adalah sebuah penjelasan dari Aqidah Ahl as Sunnah wal Jama^ah, yaitu Aqidah Imam Abu Hanifah, (meninggalkan 150 H) dan dua sahabatnya, Imam Abu Yusuf al-Qadi and Imam Muhammad Ibn al Hasan ash-Shaybaniyy serta lainnya. Dia menulis: “Dia di luar dari memiliki batas tempat atas-Nya, atau dibatasi, atau memiliki bagian-bagian atau anggota tubuh. Tidaklah Dia dikenai arah sebagaimana makhluk.” Demikian perkataan Imam Abu Ja^far yang merupakan salah ulama as-Salaf. Dia secara jelas menyatakan bahwa Dia terbebas dari dikenai 6 arah: atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang.
Ahli bahasa dan ulama hadith, Imam Muhammad Murtada az-Zabidiyy, meriwayatkan secara bersambung dari dia sendiri hingga Imam Zayn al-^Abidin ^Aliyy Ibn al-Husayn Ibn ^Aliyy Ibn Abi Talib, (juga di antara as-Salaf, bergelar as-Sajjad, yang banyak bersujur), bahwa Zayn al-^Abidin mengatakan dalam as Sahifah as-Sajjadiyyah mengenai Allah:

artinya: “Mahasuci Engkau Ya Allah, dari segala ketidaksempurnaan, Zat yang tidak ada tempat membatasi-Mu”
Dia juga berkata:

artinya: “Mahasuci Engkau, Ya Allah, dari segala ketidaksempurnaan. Zat yang tidak ada tempat membatasi-Mu”
Ketika menjelaskan Sahih Al-Bukhari bab Al-Jihad Hafidh Ibn Hajar mengatakan,”Kenyataan bahwa kedua arah atas dan bawah adalah mustahil disifatkan kepada Allah, tidak berarti bahwa Allah tidak dapat disifati dengan ketinggian, karena sifat ketinggian dari Allah adalah mengenai kedudukan dan ketidakmungkinan terletak pada sifat fisik”.
Imam Zayn ad-Din Ibn Nujaym, ulama Hanafiah, dalam buku Al-Bahr ar Ra’iq, hal 129: “Siapa yang mengatakan bahwa mungkin bagi Allah untuk berbuat tanpa keadilan/kebijaksanaan telah bertindak dosa, dan berdosa juga dia yang memastikan tempat bagi Allah Ta’ala”.
Imam Ahmad ar-Rifa^iyy al-Kabir, (600 H) berkata:

artinya: “Pengetahuan utama mengenai adalah adalah memastikan/meyakini bahwa Allah ada tanpa bagaimana dan tempat”
Imam Muhammad Ibn Hibah al-Makkiyy, dalam buku Hada’iq al-Fusul wa Jawahir al-'Uqul,–juga disebut Al-^Aqidat-as-Salahiyyah karena dia memberinya sebagai hadiah kepada Sultan Salah-ad-Din al-Ayyubiyy yang telah meminta buku ini untuk di ajarkan pada anak-anak di sekolah-sekolah dan disiarkan dari atas menara – berkata:

artinya: “Allah SWT itu ada abadi dan tidak ada tempat bagi-Nya, dan keputusan bahwa keberadaan-Nya sekarang sebagaimana Dia dahulu, yaitu tanpa tempat”
Imam Ja'far as-Sadiq, salah satu ahlul bait Nabi saw. berkata: “Orang yang menyatakan bahwa Allah berada dalam sesuatu atau di atas sesuatu atau dari sesuatu, telah berbuat kesyirikan. Karena jika Dia di dalam sesuatu, maka Dia terlingkupi/dibatasi, dan jika Dia di atas sesuatu berati Dia dibawa (sesuatu). Dan jika Dia dari sesuatu, berarti Dia seperti makhluk.”
Shaykh 'Abdul-Ghaniyy an-Nabulsiyy berkata: “Dia yang percaya bahwa Allah memenuhi langit dan bumi atau bahwa Dia adalah duduk secara fisik di atasal-^arsh (Singgasana) dia telah kafir.”
Imam Abul-Qasim 'Aliyy Ibnul-Hasan Ibn Hibatillah Ibn ^Asakir berkata dalam bukunya Aqidah: “Allah telah ada sebelum penciptaan. Dia tidak memiliki sebelum dan sesudah, atas atau bawah, kanan atau kiri, di depan atau di belakang, sebagian atau seluruh. Tidak bisa dikatakan kapan bagi Dia, di mana bagi Dia, atau bagaimana bagi Dia. Dia ada tanpa tempat”.
Imam Abu Sulayman al-Khattabiyy berkata: “Apa yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk diketahui adalah bahwa Tuhan kita tidak memiliki bentuk, karena bentuk memiliki “bagaimana”, dan “bagaimana” tidak berlaku bagi Allah atau disifatkan bagi-Nya. Mengetahui tanpa ragu bahwa pertanyaan “bagaimana” tidak berlaku bagi Allah, karena ini adalah pertanyaan tentang bentuk, tubuh, tempat, kedalaman, dan dimensi, Allah Mahasuci dari segala hal itu.
Imam al-Ghazaliyy berkata: ” Allah, Ta’ala, ada selamanya dan tidak memerlukan tempat. Dia bukan tubuh, jauhar (atom), atau benda, dan Dia tidak di atas suatu tempat atau di dalam suatu tempat.”
Segala pernyataan ini menunjukkan bahwa mensifatkan ketinggian dan tempat yang bersifat fisik adalah bertentangan denganAl-Quran, Hadis, Ijma’ dan dalil akal. Bukti akal bahwa Allah ada tanpa tempat, terletak pada fakta bahwa sesuatu yang berada di dalam suatu area, dan sesuatu yang memiliki suatu tempat adalah memerlukan tempat, dan bahwa sesuatu yang membutuhkan yang lain bukanlah Tuhan. Lebih lanjut, sebagaimana akal menyatakan bahwa Allah ada tanpa berada di suatu tempat sebelum tempat diciptakan, dan akal menyatakan bahwa Allah menciptakan tempat-tempat dan tetap ada tanpa suatu tempat.
Ulama seperti Imam Ahmad ar Rifa'iyy menyatakan bahwa mengangkat tangan dan wajah ketika melakukan doa adalah karena langit adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka’bah adalah kiblatnya salat. Dari langit kasih dan rahmat dari Allah turun.
Dengan demikian, adalah jelas bagi orang yang mencari kebenaran tentang Allah ada tanpa memerlukan tempat adalah sesuai dengan Quran, Hadis, Ijma’ dan pedoman akal yang jelas. Yakinkan bahwa sebelum tempat diciptakan, Allah Yang Menciptakan segala sesuatu (termasuk tempat dan lainnya) ada tanpa tempat, dan sesudah tempat tercipta Allah tetap tidak memerlukan tempat.
Karena kita sebagai Muslim berkeyakinan adalah bahwa Allah ada tanpa berada/memerlukan tempat dan bahwa pertanyaan “bagaimana” tidak berlaku bagi Allah, maka adalah jelas bagi kita bahwa Arsy (singgasana) yang merupakan ciptaan Allah terbesar dan merupakan langit-langit sorga, adalah bukan tempat bagi Allah SWT.
Imam Abu Mansur al-Baghdadiyy menyatakan bahwa Imam ^Aliyy Ibn Abi Talib kw. berkata:

artinya: “Allah menciptakan Arsy sebagai tanda Kekuasaan-Nya dan tidak menjadikan sebagai tempat bagi-Nya.”
Imam Abu Hanifah dalam al Wasiyyah, berkata: ” … dan Dia adalah Penjaga Arsy dan selain Arsy, tanpa memerlukannya, Dia-lah yang diperlukan… Lagian, Apakah Dia ada di suatu tempat yang diperlukan untuk duduk dan istirahat, sebelum Arsy diciptakan? Dimana Allah ketika itu?”. Jadi, pertanyaan “Di mana Allah” tidak berlaku bagi-Nya, karena tidak mungkin.
Juga, dalam bukunya Al-Fiqh al-Absat, Imam Abu Hanifah berkata: “Allah selalu ada abadi, dan tidak memerlukan tempat, makhluk atau barang, tetapi Dia-lah Pencipta segala sesuatu. Orang yang berkata ‘Saya tidak tahu apakah Tuhanku ada di bumi atau di langit” adalah kafir. Juga kafir orang yang mengatakan ‘Dia ada di atas Arsy tetapi saya tidak tahu apakah Arsy ada di langit atau di bumi.’”
Lebih lanjut, Imam Abu Hanifah menyatakan kafir siapa yang mengatakan kedua frasa di atas karena mereka mengandung penyifatan dengan arah, batasan, dan tempat bagi Allah. Segala sesuatu yang memiliki arah dan batas adalah secara logika memerlukan Pencipta. Jadi, bukan maksud Imam Abu Hanifah untuk membuktikan bahwa Langit dan arsy adalah tempat bagi Allah, sebagaimana mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya mengklaim. Ini adalah maksud Imam Abu Hanifah mengatakan, “Apakah Dia berada di dalam suatu tempat untuk duduk dan istirahat? Lalu sebelum arsy tercipta, dimana Allah?”, yang menunjukkan dengan jelas penolakan bahwa Allah memiliki arah atau tempat.
Dalam bukunya Ihya’ 'Ulum ad-Din, Imam al Ghazaliyy mengatakan: “… tempat tidaklah meliputi Dia, tidak juga arah, bumi maupun langit. Dia disifati istiwa atas arsy sebagaimana dikatakan Quran – dengan arti yang Dia kehendaki – dan tidak juga sebagaimana orang yang mungkin … Itu adalah istiwa yang bebas dari sentuhan, istirahat, pegangan, gerakan, dan pelingkupan. Arsy tidak membawa Dia, tetapi justru arsy dan apa yang membawa arsy seluruhnya dibawa/dijaga oleh Allah dengan Kekuasaan-Nya dan dikuasai-Nya. Dia mengatasi arsy atau langit dan mengatasi segala sesuatu – dalam kedudukannya – suatu ketinggian yang tidak mendekat ke Arsy atau langit, sebagaimana juga tidak menjauh dari bumi. Dia adalah Lebih Tinggi dalam kedudukan daripada segala sesuatu: lebih tinggi dari arsy atau langit, sebagaimana Dia adalah Lebih Tinggi dalam kedudukan daripada langit dan seluruh makhluk.
Shaykh ^Abdul-Ghaniyy an-Nabulsiyy berkata: “Orang yang percaya bahwa Allah mengisi langit dan bumi atau bahwa Dia adalah jasad yang duduk di atas arsy, dia telah kafir. Ayat 93 Surat Maryam:

artinya: “Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. (QS. 19:93)
Dalam Tafsirnya Imam Ar-razy berkata:” … dan karenanya jelas dengan ayat ini bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah seorang hamba bagi Allah, dan karenanya adalah pasti bahwa Allah adalah Mahasuci dari menjadi (memiliki sifat) sebagai hamba, sehingga Dia Mahasuci dari sifat berada di tempat atau arah, atau di atas arsy atau kursi”.
Dengan demikian Surat Taha, ayah 5, dalam Qur’an:

dengan jelas tidaklah berarti bahwa Allah duduk di atas singgasana, atau bahwa Allah menetap di atas singgasana. Dalam bahasa Arab, kata istawa memiliki 15 makna yang berbeda, di antaranya duduk (to sit), menguasai (to subjugate), menjaga (to protect), mengalahkan (to conquer) dan memelihara (to preserve). Berdasar apa yang telah kita bahas di atas adalah tidak benar memahami ayat tersebut dengan arti “duduk” bagi Allah. Ada pun makna memelihara dan menjaga bersesuaian dengan pemahaman agama dan bahasa.
Imam Hafidh Ibn Rajab al-Hanbaliyy mengartikan al-istiwa’ dengan al-istila’, yang berarti menguasai tanpa sebuah awal. Yaitu, Allah mensifati Diri-Nya dengan menguasai Arsy sejak al-azal (keadaan tanpa awal, yaitu sebelum penciptaan). Karena al-Arsy adalah ciptaan Allah yang terbesar, dan dia dikuasai oleh Allah, maka segala sesuatu yang lebih kecil dari Al-Arsy juga dibawah kendali Allah.
Dinyatakan mengenai Imam Malik bin Anas oleh Al-baihaqi melalui sanad yang sahih dari jalur Abdullah bin Wahb bahwa, “Kami berada di dalam rumah Imam Malik ketika seorang lelaki masuk dan berkata, ” Wahai Aba Abdillah (Imam Malik), Ar-Rahmanu ‘alal ‘arsy istawa. Bagaimana Dia istawa?”. Imam Malik melihat kebawah dengan terperanjat kemudian dia mengangkat muka dan berkata, “Alal ‘arsy istawa sebagaimana Dia mensifati untuk Dirinya. Tidak benar untuk mengatakan “bagaimana” karena “bagaimana” tidak berlaku bagi-Nya. Saya lihat bahwa kamu seorang ahli bid’ah. Keluarkan dia”. Dengan demikian, perkataan Imam Malik, “Bagaimana tidak berlaku bagi-Nya”, berarti bahwa Istiwa-Nya atas Arsy-Nya tanpa “bagaimana”, yaitu tanpa jasad, tempat, bentuk atau form seperti duduk, persentuhan, meletakan di atas, dan yang semacamnya.
Karenanya, tidak ada dasar perkataan mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang disandarkan kepada Imam Malik, bahwa al-istiwa telah diketahui, dan bagaimana adalah tidak diketahui. Apa yang mereka maksudkan bahwa istiwa adalah duduk, tetapi bagaimana duduk-Nya adalah tidak diketahui. Perkataan ini tidak benar, karena duduk itu, tidak masalah bagaimana dia, akan dilakukan dengan anggota tubuh dan bagian yang dapat ditekuk. Dengan demikian, perkataan yang disandarkan kepada Imam Malik tidak terbukti dari Dia atau yang lainnya.
Imam al-Lalaka’iyy meriwayatkan dari Umm Salamah and Rabi'ah Ibn Abi 'Abdar-Rahman:

artinya: “Istiwa tidak asing (majhul) – karena disebut dalam Al-Quran – dan “Bagaimana” tidak masuk akal – karena tidak mungkin berlaku bagi Allah”. Sehingga, Hadis dan Ayat Quran yang mensifati ketinggian kepada ALlah, merujuk kepada ketinggian kedudukan dan bukan ketinggian tempat, arah, sentuhan atau perletakan.
Dalam Surat al-An^am ayat 61, Allah berfirman:

artinya: “Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua hamba-Nya”. Dengan demikian “fauqa” (ketinggian) dalam ayat ini adalah dalam kekuasaan bukan dalam arti tempat atau arah.
Hati-hati dengan apa seperti dikatakan Translation of the Qur’an oleh Yusuf Ali dan dikatakan sebagai versi revisi (dari Yusuf Ali) dan dicetak olehKing Fahd Holy Qur’an Printing Complex di al-Madinah al-Munawwarah, di halaman 879, dalam menterjemahkan ayah 5 Surat Taha:

mereka katakan: “The Most Gracious is firmly established on the throne,” (Yang Maha Penyayang bersemayam di atas singgasana). Dan di catatan kaki mereka katakan dengan jelas:”Who encompasses all creation and sits on the throne.” (Yang meliputi segala ciptaan dan duduk di atas singgasana)
Begitu juga, hati-hati dengan bagian lain yang menyerupakan Allah dengan makhluk seperti pada halaman 1799 dalam ayah 42 Surat al-Qalam:

mereka mensifati “betis” kepada Allah.
Pada halaman 1015 dalam mentafsirkan Surat An-Nur ayat 35:

mereka mengatakan: “Allah adalah cahaya” dan dalam catatan kaki mereka dengan jelas mengatakan:”We can only think of Allah in terms of our phenomenal experience.”(Kita hanya bisa memikirkan dalam arti pengalaman keseharian kita)
Al-Musyabbihah adalah mereka yang menserupakan Allah dengan makhluk; mereka percaya bahwa Allah menyerupai makhluk. Mereka mensifati Allah dengan tempat, arah, bentuk dan badan, dan mereka mencoba menutupinya dengan mengatakan; “Bagaimana pun, kita tidak tahu bagaimana tempat-Nya, atau bagaimana Dia duduk, atau bagaimana Wajah-Nya, atau bagaimana betis-Nya, bagaimana Cahaya-Nya”. Semua hal itu jelas menunjukkan kesalahan mereka.
Puji syukur kepada Allah Tuhan Semesta alam, Zat yang suci dari penyerupaan dengan dengan makhuk, segala sifat yang tidak layak, dan segala yang tidak benar tentang Dia.
===============================
Jelaslah bahwa :
1. Para para sahabat, Tabi’ien, Tabi’ut Tabi’iIn, imam Mazhab dan semua ulama Ahlus Sunnah telah bersepakat tentang pe-nafi-an Alloh atas tempat dan zaman (ruang dan waktu)
2. Alloh adalah kholiq dan selainnya adalah makhluq. Tidak ada kebutuhan khaliq atas makhluq. Bahkan sebaliknyalah, makhluq bergantung pada kholiq.
3. Alloh menciptakan Arsy dan langit sebagai manifestasi dari kemahakuasaanNYA dan sama sekali bukan untuk tempat bagi dzat Alloh yang maha mulia.
4. Dzat Alloh tidak berubah dari sebelum diciptakan apa pun sampai sekarang, akhir zaman dan sampai kapan pun.
5. Ulama Ahlus Sunnah telah dengan jelas menerangkan kepada kita sebagai panduan yang terang benderang. Adapun Wahhabi berusaha untuk mengaburkan dan membawa kepada kesesatan.
===============================
Jelaslah bahwa :
1. Para para sahabat, Tabi’ien, Tabi’ut Tabi’iIn, imam Mazhab dan semua ulama Ahlus Sunnah telah bersepakat tentang pe-nafi-an Alloh atas tempat dan zaman (ruang dan waktu)
2. Alloh adalah kholiq dan selainnya adalah makhluq. Tidak ada kebutuhan khaliq atas makhluq. Bahkan sebaliknyalah, makhluq bergantung pada kholiq.
3. Alloh menciptakan Arsy dan langit sebagai manifestasi dari kemahakuasaanNYA dan sama sekali bukan untuk tempat bagi dzat Alloh yang maha mulia.
4. Dzat Alloh tidak berubah dari sebelum diciptakan apa pun sampai sekarang, akhir zaman dan sampai kapan pun.
5. Ulama Ahlus Sunnah telah dengan jelas menerangkan kepada kita sebagai panduan yang terang benderang. Adapun Wahhabi berusaha untuk mengaburkan dan membawa kepada kesesatan.
Langganan:
Postingan (Atom)